Seputar Batavia
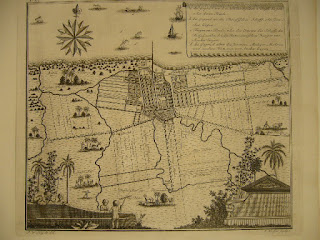 |
| Peta Ommelanden (sekitar Batavia) |
Penutupan abad kedelapan belas menyaksikan terkoyaknya
keamanan publik di Ommelanden Batavia.
Gerombolan-gerombolan yang berkeliaran menyatroni kawasan itu, pembunuhan
merajalela, mengacau ketertiban, dan pertempuran kecil-kecilan antar-kelompok
etnis bahkan terjadi di tempat-tempat terpencil. Di Tangerang, di perbatasan
dengan Banten, orang Cina dan Jawa bentrok, beberapa kampung dibakar, dan tak
jauh dari situ, warga Belanda dan bekas heemraad
Andries Teisseire dibunuh para bandit. Di sebelah timur Batavia, di Marunda,
penduduk setempat bersekutu dengan pasukan Inggris. Pihak berwenang mengalami
kesulitan besar untuk menghimpun keterangan intelijen tentang situasi saat itu
dan memulihkan ketertiban. Bahkan sesudah 180 tahun kehadiran Belanda, sangat
terasa bahwa kontrol Belanda atas Ommelanden sangat rapuh.
[ … ]
Pemukiman di Ommelanden muncul dari dua arah. Mula-mula,
tentu saja, berlangsung eksplorasi dan pembudidayaan bertahap hutan-hutan di
sekitar Batavia. Pada tahun 1620-an, orang Belanda dan Cina membersihkan lahan
di luar tembok kota dan menanam kelapa. Eskpansi ini terutama mengarah ke selatan,
di sepanjang Sungai Ciliwung. Sebelah timur dan barat kota tanahnya bergambut
dan tidak cocok untuk bercocok tanam dan pemukiman hingga sistem drainase kanal
dan parit menyingkirkan halangan-halangan paling buruk ini. Selain proses
terkenal penggarapan lahan yang dilakukan para pengusaha kota itu, terjadi pula
imigrasi dan pemukiman perlahan-lahan namun terus meningkat dari orang-orang
Jawa, baik dari barat, dari wilayah Banten, maupun dari timur,
provinsi-provinsi Mataram. Apa pun alasan politis atau ekonomi mereka, yang
jelas para imigran terus mengalir, dan berbondong-bondong mendatangi wilayah
yang dikontrol Kompeni di sekitar Batavia atau daerah tak bertuan di pegunungan
di selatan Batavia. Walaupun Kompeni berusaha mengonsentrasikan orang Jawa di
satu tempat, mereka memperlihatkan kecenderungan meningkat untuk menyebar ke
segala penjuru pedalaman, menetap di tanah milik pribadi, atau di daerah-daerah
tak bertuan yang jauh dari kota.
Baru sesudah tahun 1650 pihak berwenang menyatakan
bertanggung jawab untuk mengarahkan, melindungi, dan membantu pembersihan tanah
di Ommelanden. Fase campur tangan pemerintah ini dipicu oleh ancaman militer
dari Banten, pertambahan penduduk Ommelanden, dan peningkatan konflik atas kepemilikan
dan batas tanah. Sebuah langkah penting dilakukan pada tahun 1656–1657 berupa
pembangunan enam benteng kecil sejauh satu hingga dua kilometer dari tembok
kota. Sebuah badan terpisah, heemraden,
dibentuk untuk mencatat hibah tanah dan mengelola jalan serta angkutan air.
Periode ini juga ditandai dengan dua pengembangan aturan yang
sepenuhnya berbeda, yang akan mengubah secara dramatis penampilan Batavia.
Salah satunya adalah keputusan pemerintah untuk melarang semua orang Jawa
berada di dalam tembok kota dan mengonsentrasikan mereka di beberapa lokasi di
Ommelanden, dipimpin oleh kepala kampung mereka masing-masing dan diawasi oleh
seorang pejabat Eropa. Langkah ini menjadi model selama 150 tahun berikutnya,
yang dalam kurun itu kehidupan Muslim nyaris disingkirkan dari dalam kota.
Peristiwa lainnya, terjadi pada tahun 1656, adalah kedatangan rombongan pertama
pasukan bantuan dari Kepulauan Ambon. Mereka ditundukkan oleh Panglima Arnout
de Vlamingh van Outshoorn dan selanjutnya dimasukkan ke dalam dinas militer
Kompeni. Sesekali mereka bertempur dalam ekspedisi militer besar-besaran
Kompeni selama periode itu: Sailan, Sumatra, dan Sulawesi. Walaupun kebanyakan
orang Ambon lebih sering bertugas di luar negeri ketimbang di Batavia, mereka
diberi sebidang tanah di dekat Marunda, sebelah timur Batavia yang berbatasan
dengan Karawang.
Orang-orang Ambon itu segera disusul oleh pasukan-pasukan
lain, Makassar, Bugis, dan Bali yang diperlakukan sama seperti orang-orang
Ambon. Hampir tanpa perkecualian, mereka diundang ke Batavia setelah dibujuk
masuk dinas militer Kompeni selama berbagai ekspedisi militer di Kepulauan
Ambon, di Sulawesi selatan, atau di Jawa. Dengan cara itu, Kompeni memastikan
loyalitas kelompok-kelompok yang sebagian besar dahulu adalah musuhnya. Salah
satu contoh terakhir prosedur ini adalah bangsawan Bali Gusti Ktut Bedahulu
yang, setelah memerangi Kompeni di Jawa timur, menyerah kepada Belanda pada
tahun 1708 dan dihadiahi sebidang tanah sebagai imbalan di Bacherachsgracht di
sebelah barat kota. Menjadi tulang punggung sistem kampung, kelompok-kelompok
militer itu diikuti dan segera dikalahkan jumlahnya oleh banyak budak yang
dibebaskan yang menetap di Ommelanden, waktu berlalu dan pemerdekaan budak
menjadi pemasok utama bagi komunitas kampung (kecuali orang Jawa, yang jarang
terwakili dalam populasi budak, dan yang komunitasnya membesar hanya dengan
imigrasi “bebas”).
Meningkatnya jumlah orang Jawa dan penduduk Indonesia
lainnya setelah tahun 1656 menyodorkan beberapa problem bagi pihak berwenang,
dan pemisahan tampaknya menawarkan solusi. Salah satu problem adalah dugaan
ancaman terhadap ketertiban publik dari kelompok-kelompok tentara itu, juga
kemungkinan bentrok antara berbagai kelompok tersebut. Problem lainnya adalah
keengganan pemerintah untuk campur tangan dalam urusan-urusan pribumi atau
dalam administrasi hukum pidana. Selanjutnya, diharapkan komunitas-komunitas
itu bisa dimobilisasi dengan mudah apabila Kompeni membutuhkan tentara.
Perlahan-lahan berkembang sebuah sistem untuk mengatur kelompok-kelompok yang
baru tiba di Batavia; tetapi baru pada tahun 1686, ketika sebuah gardu jaga
kota diserang bandit-bandit Bali, pemerintah memutuskan untuk menuntaskan
persoalan kelompok-kelompok Indonesia, dan menerbitkan berbagai peraturan
terperinci yang mencakupi seluruh komunitas di Ommelanden. Diangkatlah para
kepala kampung yang memperoleh pangkat kapten. Mereka mendapat imbalan tanah
untuk menopang hidup mereka dan menampung para pengikut mereka. Dengan cara ini
berbagai komunitas dijauhkan dari dalam kota, menegakkan yurisdiksi sipil dalam
komunitas masing-masing, mencukupi diri sendiri, dan mudah dimobilisasi dengan
perantaraan para kepala kampung yang ditunjuk. Dengan demikian prinsip
administratif kolonial pemerintahan tidak langsung dalam skala kecil tercermin
di Ommelanden.
Kebijakan pemisahan berbagai komunitas Indonesia
menyerupai, dan barangkali ditopang oleh, praktek yang lazim berlaku di
kebanyakan kota bandar Asia Tenggara yaitu memberikan wilayah khusus bagi
komunitas dagang asing dan menjamin kebebasan pelaksanaan yurisdiksi mereka
sendiri. Berbagai prakarsa untuk mencapai tujuan serupa sesungguhnya juga
dilakukan di Batavia pada tahun 1620-an dan 1630-an, dalam skala kecil, dan lambat
laun semacam pemisahan sendiri terjadi di kalangan Mardijker (Kristen Asia),
Cina, dan yang disebut Moor (Muslim India) di beberapa pinggiran kota. Tetapi
pemisahan kelompok-kelompok Indonesia yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan bertolak belakang dengan proses pemisahan diri tersebut dalam
ihwal keketatan aturan formalnya dan (sebagian) dalam tujuan-tujuannya.
Pemisahan itu didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan, dan pada saat bersamaan
dimaksudkan untuk mengatasi persoalan keamanan publik di Ommelanden dan
keruwetan administratif yang disebabkan oleh kehadiran kelompok-kelompok etnis
yang sangat beragam itu.
Berbagai komunitas Indonesia tetap menjalankan fungsi
militer mereka hingga akhir periode VOC. Bahkan pada tahun 1773 pemerintah
mengharapkan para perwira Indonesia “[...] agar mereka selalu siaga dan
bersedia ditugaskan dalam salah satu ekspedisi [...].” Sedikit demi sedikit
perekrutan bahkan mencapai tugas di kapal-kapal Kompeni sewaktu Kompeni semakin
kesulitan melengkapi kapal-kapal mereka dengan para pelaut dari Republik Belanda.
Baru pada tahun 1780-an, ketika kekurangan tenaga kerja menjadi sangat gawat
dan penduduk kampung-kampung Batavia makin enggan diikutsertakan, Kompeni
berpaling ke sumber-sumber lain. Makin banyak orang yang direkrut di Madura, di
sepanjang pantai utara Jawa, bahkan di wilayah-wilayah kerajaan Surakarta dan
Yogyakarta.
Dipetik dari Remco Raben, Seputar Batavia: Etnisitas dan otoritas di Ommelanden, 1650–1800,
dalam Jakarta Batavia: esai sosio
kultural, penyunting: Kees Grijns dan Peter J.M. Nas, penerjemah: Gita
Widya Laksmini dan Noor Cholis, Banana, KITLV, Jakarta, 2007.
Sumber gambar: https://driwancybermuseum.wordpress.com/page/17/?newwi

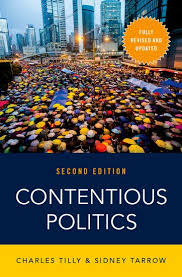

Comments
Post a Comment