Ritual diplomatik Batavia
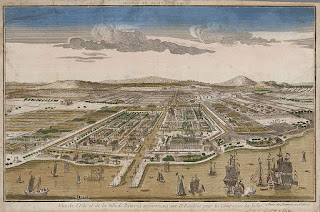 |
| Batavia (c. 1780) |
Setiap kali peran historis ibu kota Indonesia dalam
perjuangan merebut kemerdekaan disinggung, sepertinya julukan yang paling tepat
untuk dilekatkan kepadanya adalah kota diplomasi. Selama empat tahun yang
merentang antara Proklamasi Kemerdekaan pada Agustus 1945 dan penyerahan
kedaulatan pada tahun 1949, Jakarta menjadi pusat kegiatan pengumpulan data
intelijen. Bersamaan dengan itu ibu kota berfungsi sebagai sebuah laboratorium
di mana para juru runding pemerintah kolonial Belanda dan Republik Indonesia yang
masih muda bisa menguji strategi-strategi politik mereka. Di bagian Jawa yang
lain pertempuran berlanjut.
Di kubu Republiken terdapat perbedaan pendapat antara
mereka yang meyakini bahwa kemerdekaan harus dicapai lewat diplomasi, dengan
demikian menghindari korban nyawa berlebihan dan penderitaan, dan mereka yang
percaya bahwa merdeka hanya bisa direbut melalui perjuangan bersenjata.
Argumen-argumen serupa juga bisa ditemukan di kubu
Belanda. Strategi-strategi yang disusun para pejabat sipil di meja perundingan
dimaksudkan untuk memandulkan republik muda itu di Jawa Tengah dalam jaringan
sistem negara konfederasi. Sesungguhnya, inilah tujuan akhir Perundingan
Linggadjati. Di lain pihak, militer Belanda berteriak lantang bahwa waktu yang
amat berharga hilang ketika negosiasi berlangsung: makin lama para
“pemberontak” diberi peluang untuk memperkuat diri, akan semakin sulit menumpas
mereka.
Kedudukan Jakarta dalam konflik ini tidak menentu. Bagi
bangsa Indonesia kota itu adalah tempat kelahiran Republik baru, sebab Sukarno
dan Hatta menyatakan Proklamasi
Kemerdekaan di kota proklamasi ini di kediaman Sukarno pada tanggal 17 Agustus
1945. Bagi Inggris beberapa pekan kemudian, Jakarta adalah tempat musuh
menyerah, di mana tentara Inggris akan menerima penyerahan pasukan Jepang. Bagi
Belanda, tak lama sesudah itu, Batavia—belum Jakarta—akan menjadi pangkalan
bagi kampanye militer Belanda untuk menguasai kembali wilayah mereka yang lepas
di pulau Jawa begitu mereka sudah cukup kuat. Daerah itu begitu tidak stabil sehingga
pada tanggal 4 Januari 1946 para petinggi pemerintahan Republik,
mengkhawatirkan keselamatan mereka, dipaksa mengemasi barang-barang pribadi
mereka dan bertolak ke Yogyakarta.
Begitu Perserikatan Bangsa-Bangsa campur tangan, otoritas
kolonial Belanda tidak pernah mampu melaksanakan rencana untuk menegakkan
kembali hegemoni di medan perang. Ketika kampanye militer besar-besaran mereka,
atau “aksi polisional”, akhirnya dilancarkan pada tahun 1947 dengan dalih
memulihkan hukum dan ketertiban, protes internasional sedemikian sengitnya
hingga penyerbuan itu kedodoran dari sudut pandang politik, meski pada mulanya
terlihat sebagai kesuksesan strategis.
Selama empat tahun perjuangan kemerdekaan, Yogyakarta
menjadi basis mutlak faksi perjuangan. Yogya menjadi pusat simbolis perlawanan
ketika keraton Sultan Hamengkubuwono berubah menjadi markas besar perjuangan
Revolusioner, sementara Jakarta tetap merupakan pementasan wayang politik. Para
anggota misi asing, para juru runding serta penengah datang dan pergi. Ditilik
dari memoar pribadi dan catatan-catatan kontemporer, pertarungan diplomatik di
balik layar dipenuhi tindakan sembrono, ilusi, itikad yang disalahpahami, dan
ketidakpastian yang umumnya menyertai pembuatan keputusan, Benedict Anderson
mengatakan: “Jika seseorang hidup di Djakarta kosmopolitan yang diduduki, sulit
untuk tidak mempercayai mutlaknya kebutuhan akan diplomasi. Tetapi jika orang
itu hidup di Jogjakarta tradisional yang tidak diduduki, di mana wajah kulit
putih jarang terlihat, bagaimana orang itu bisa tidak percaya, mengamati dan
mengalami vitalitas bergolak kota itu, bahwa perlawanan mungkin dan harus
dilakukan?” (Anderson 1972: 301).
Meski begitu di meja perundinganlah monster pemerintahan
kolonial akhirnya terbantai pada tahun 1949. Beberapa tahun kemudian, pada
Konferensi Bandung 1955, Republik Indonesia, dianggap sudah cukup umur di
pentas diplomasi internasional, menyelenggarakan konferensi tingkat dunia
pertama untuk negara-negara non-blok.
Dilihat dalam kilas balik, terlihat nyaris ironis bahwa
tempat menonjol Indonesia dalam keluarga bangsa-bangsa melekat sangat erat
dengan lokasi perhelatan tersebut, sebuah kota yang di mata orang Betawi tak
lain hanyalah pertumbuhan dari sebuah bukit peristirahatan bagi orang kota yang
kepanasan. Harga diri daerah yang terkoyak mengatakan bahwa Konferensi Bandung
tidak mengizinkan Jakarta menyandang mutiara di mahkotanya.
Penduduk kota diplomasi boleh jadi merasa terhibur dengan
gagasan bahwa Batavia/Jakarta, yang menyimpan tradisi panjang sebagai makelar
kekuasaan untuk berbagai hubungan internasional di Asia Tenggara, nyaris tidak
membutuhkan sehelai bulu lagi untuk mempercantik hiasan kepalanya. Seorang
warga Jakarta yang gusar hanya perlu mengingat kembali lalu lintas diplomatik Zaman
Kompeni yang hampir terlupakan. Hingga permulaan abad kedua puluh, para duta
dari kerajaan-kerajaan Jawa dan utusan dari “raja-raja pribumi” luar Jawa melakukan
kunjungan kehormatan kepada gubernur jenderal, “Kepala Pemerintahan Hindia
Belanda”, di Batavia, yang kala itu dikenal sebagai “Ratu dari Timur”.
[ ... ] tiga ratus tahun silam pemerintah Batavia
mendapat tempat di antara para penguasa Asia dan berusaha mengikuti aturan main
yang kala itu dianggap sebagai etiket dan protokol diplomatik Asia. Para
kolonis Belanda tentu tidak perlu menciptakan ritual “oriental” guna
menyesuaikan dengan konvensi yang berlaku dalam melakukan hubungan luar negeri
pada tataran diplomatik di Hindia Timur. Ketika menyebut kata “diplomasi”,
istilah itu saya pakai untuk menunjuk proses di mana berbagai pemerintahan
bertindak melalui agen-agen resmi yang saling berkomunikasi. Struktur sistem
upeti dunia “diplomatik” Timur agak membingungkan para pendatang baru Belanda.
Mereka harus mencebur ke dalam kolam bergolak sistem lokal tata dunia
hierarkis, yang dirajut oleh relasi kekuasaan vertikal yang terus bergeser di
mana pemberian upeti terlebih dahulu ada daripada hubungan diplomatik relatif
horizaontal yang lazim di pentas Eropa, yang dari situ Hugo Grotius mendapatkan
ide orisinalnya tentang hukum internasional.
Sejauh mana persepsi Belanda tentang relasi kekuasaan
Indonesia dan representasi kekuasaan politik dalam perilaku ritual benar dan
tepat masih, hingga penelitian lebih lanjut dilakukan, terbuka untuk
dipertanyakan. Proses aktual di mana kehadiran Belanda di Hindia Timur mengakar
dalam jaringan politik imperium Cina dan Mogul yang jauh dan tata dunia
hierarkis yang berorientasi lebih regional para penguasa Jepang, Muang Thai,
Birma, Sailan atau Jawa adalah subjek yang sejauh ini hanya mendapatkan sedikit
perhatian dari para sejarawan. Pada masa lalu, ekspansi Eropa di Asia dikaji
sebagai gerakan penghancuran sepihak, sedangkan saat ini para sejarawan Asia
Tenggara berupaya serius menulis sebuah sejarah otonom yang cenderung
mengesampingkan keterlibatan Eropa dalam proses historis Asia Tenggara.
Sekaranglah saatnya menyingkirkan kedua pandangan historis timpang itu dan
mengakui bahwa, di tengah berbagai persekutuan yang berubah dalam politik Asia
Tenggara abad ketujuh belas dan kedelapan belas, kemunculan Kongsi Dagang
Hindia Belanda sebagai kekuatan teritorial dan maritim yang berhadap-hadapan
dengan para tetangganya terus-menerus ditantang. Yang membikin frustrasi
Pemerintah Tinggi (Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia) di Batavia, persekutuan
antara berbagai penguasa regional terus mengalami pergeseran dan Belanda selalu
terancam terseret dalam sengketa-sengketa lokal yang sedikit sekali sangkut pautnya
dengan mereka. Dalam hal ini prinsiplah, bukan politik, yang menentukan urusan
diplomatik penguasa-pedagang dan prinsip mereka adalah keuntungan komersial, jangan
sampai ada kekeliruan soal ini. Di mata Pemerintah Tinggi campur tangan dalam
pertikaian lokal dan pembentukan dominion mutlak tetap merupakan gagasan mahal
yang harus dihindari sebisa mungkin.
Alhasil, Pemerintah Tinggi di Batavia dengan sadar
memanfaatkan sisi seremonial hubungan luar negeri untuk menegakkan kendali atas
kepulauan Asia Tenggara, seraya berusaha keras menghindari segala komitmen
terhadap campur tangan aktual dalam urusan politik bangsa-bangsa yang tidak
memberi kontribusi langsung bagi jaringan perdagangannya. Di samping mengontrol
wilayah yang dikuasai langsung maupun tidak di Jawa, Ratu Batavia memegang
sebuah “supremasi laut informal” yang diperoleh dan dipelihara dengan
manipulasi atas hubungan diplomatik yang dinamis.
Dipetik dari Leonard Blussé, Ratu di antara para raja; Ritual Diplomatik di Batavia, dalam Jakarta Batavia: esai sosio kultural,
penyunting: Kees Grijns dan Peter J.M. Nas, penerjemah: Gita Widya Laksmini dan
Noor Cholis, Banana, KITLV, Jakarta, 2007.
Sumber gambar:
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Jakarta#/media/File:Ville_de_Batavia_c1780.jpg

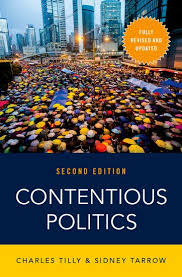
Comments
Post a Comment