Konfrontasi Sebuah Minoritas Terbelah
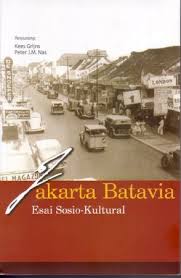 |
| Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural |
Pada tahun 1901 beberapa pemuka Arab di Batavia, antara
lain al-Aydrus bin Syihab dan Muhammad al-Faqir, mendirikan Jamiyat Khair,
Perhimpunan untuk Kebaikan. Organisasi ini bertujuan memperkuat karakter Arab komunitas,
utamanya budaya dan bahasa Arab, dengan membuka sebuah sekolah Arab di ibu kota
dan mengirimkan anak-anak muda untuk melanjutkan studi di negara-negara Arab (Menjelang 1981). Pengajaran dengan
sistem kelas diberlakukan dan, walaupun mata pelajaran agama tetap menonjol,
perhatian juga mulai diberikan bagi mata pelajaran modern seperti ilmu bumi,
aritmetika, dan bahasa Inggris (bukan Belanda). Para pendiri itu berlatar
belakang religius konservatif, tetapi di bidang lain pandangan mereka progresif
(Pijper 1977: 110). Mereka berusaha mempertemukan tantangan-tantangan abad baru
dengan nilai-nilai tradisional. Perkumpulan ini juga terbuka untuk orang Islam
bukan Arab (Noer 1973: 58). Salah seorang anggota Jawa adalah Ahmad Dahlan,
yang kemudian mendirikan Muhammadiyah.
Agar lebih mengerti tentang perkembangan di Timur Tengah,
seperti pan-Islamisme dan perdebatan tentang persoalan agama, tiga ulama
didatangkan dari dunia Arab pada tahun 1912, satu dari Sudan, satu dari Maroko,
dan satu dari Hijaz. Ahmad Surkati dari Sudan, kerabat Mahdi dari Sudan. yang
menuntut ilmu antara tahun 1896 dan 1904 di Madinah dan Makkah, menjadi tokoh
amat berpengaruh dalam komunitas Arab di dalam maupun di luar Batavia (Affandi
1976: 60). Cukup mengejutkan bagi para pemimpin Jamiyat Khair, ternyata dia
adalah pengikut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, duo modernis Mesir, yang
mengajarkan kesetaraan seluruh umat Islam dan yang mengusung ide-ide luar biasa
progresif tentang pengamalan Islam sesuai tuntutan zaman. Ide-ide Ahmad Surkati
menyemai benih silang pendapat dalam komunitas Arab dan mengobarkan perdebatan
dahsyat. Pada tahun 1914, beberapa tahun setelah dia dipaksa meninggalkan
Jamiyat Kjair, Surkati mendirikan Jamiyat al-Islah wal-Irsyad, Perhimpunan
untuk Pembaruan dan Kepemimpinan. Salah seorang pendukung paling gigihnya
adalah si “trah rendah” Umar Mangus, kapten Arab Batavia, yang menyumbang
sebesar 25.000 gulden. Sumbangan yang lebih besar lagi (60.000 gulden)
diberikan oleh sayid filantropis dan
pergaulannya luas bernama Abdullah bin Alwi Alatas, salah satu dari sedikit
orang yang mampu berdiri netral di atas pihak-pihak yang bertikai (Noer
1973:64). Seperti Jamiyat Khair, al-Irsyad terutama bergerak di bidang
pendidikan dan kebudayaan, seperti peningkatan kemampuan baca tulis di kalangan
komunitas Arab dan pemajuan adat istiadat Arab yang sejalan dengan Islam
(Pijper 1977: 113). Tetapi karena filosofi dasarnya memang berbeda, al-Irsyad
berkembang menjadi gerakan pembaruan sejati. Al-Irsyad, yang seperti saingannya
juga punya cabang dalam komunitas-komunitas Arab lain di seluruh negeri,
menjadi kubu anti-sayid atau kubu syekh, sebutan yang makin sering dipakai
untuk semua non-sayid.
Ide-ide Surkati yang paling membuat para sayid naik darah tetapi diamini oleh
hampir semua kalangan lainnya bukanlah gagasan yang berkenaan dengan persoalan
agama murni—seperti penolakannya terhadap mistisisme dan bid’ah (pembaruan
dalam tata cara ibadah), yang dianggapnya bertantangan dengan Qur’an dan
Hadits—melainkan yang berkaitan dengan masalah sosial. Ide-ide kontroversialnya
berkaitan dengan posisi mulia yang diklaim Ba’Alawi sebagai hak mereka.
Persoalan paling penting yang diperdebatkan adalah kebiasaan mencium tangan (taqbil), kesetaraan kedudukan antara
pasangan nikah (kafa’ah), perantaraan
(tawassul), dan penggunaan gelar
kehormatan sayid.
Surkati tidak menyetujui pretensi aristokratis para sayid dan menolak peran yang dipegang
sebagian dari mereka (entah yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup)
sebagai perantara antara kaum mukminin dan Allah. Islam yang diajarkan Nabi
tidak membeda-bedakan para pemeluknya menurut leluhur atau kriteria lain mana
saja. Maka dari itu, tak seorang pun berhak mendapatkan kedudukan istimewa.
Karena alasan ini, Surkati mendesak agar kebiasaan menyalami sayid dengan mencium tangan ditinggalkan
saja. Salah seorang yang pertama kali mengikuti nasihat ini di depan orang
ramai adalah Umar Mangus, sebuah tindakan yang selama bertahun-tahun
menjadikannya kambing paling hitam bagi golongan konservatif dalam komunitas
(Affandi 1976: 56). Surkati juga memaklumkan penolakannya terhadap aturan
pernikahan yang diikuti anak turun Husein. Para anggota suku Nabi Muhammad,
terutama anak turunnya, menganggap diri sebagai bangsawan agama. Pernikahan
antara seorang gadis keturunan “darah biru” dan seorang lelaki awam dianggap
tercela. Pada tahun 1912, selama menetap di Solo, Surkati memaklumkan bahwa
pernikahan antara seorang sayidah dan
seorang non-sayid mesti
diperbolehkan. Pada tahun 1914 dia mengeluarkan fatwa mengenai topik ini, yang
mengalienasi sayid konservatif
selama-lamanya. Surkati juga menentang pemahaman yang berlaku, terutama di
kalangan non-Arab, bahwa seorang sayid
bisa membantu urusan seseorang dengan Allah atau bahwa berdoa maupun bernadzar
di kuburan mereka akan mendatangkan berkah. Dia juga tak bosan-bosan menekankan
bahwa kata sayid digunakan secara
keliru sebagai gelar, makna asli kata itu sama dengan mijnheer dalam bahasa Belanda atau monsieur dalam bahasa Prancis.
Gagasan-gagasan Surkati menaungi sebuah periode panjang
intoleransi, kebencian, dan permusuhan dalam komunitas Arab, yang menyebar ke
berbagai perkampungan Arab lain di Jawa dan memancing reaksi bahkan sampai ke
Hadramaut (Bujra 1967). Hingga akhir 1930-an, pihak-pihak yang bersebarangan sering
kali saling serang dalam pidato dan media cetak atau menyudahi silang pendapat
mereka dengan adu jotos. Pada tahun 1913 sekelompok sayid mengacau rapat orang-orang al-Irsyad di rumah Syekh Isa bin
Badr. Dalam insiden itu, yang harus dihentikan oleh polisi, tiga pengikut
Surkati terluka (Affandi 1976: 120-1). Itulah seri pertama dari rangkaian aksi
kekerasan fisik di kalangan orang Arab di Hindia Belanda (De Jonge 1991: 96).
Kurang brutal tetapi tak kalah provokatif adalah tuduhan dan tuduhan balik di
surat kabar, jurnal, pamflet, dan tulisan satir. Golongan sayid menuding lawan mereka sebagai ahli bid’ah, tukang fitnah,
komunis, atau Bolshevis; kubu syekh
balik mengecam mereka sebagai pembual dan penyemu. Untuk mengejek lawan mereka,
kubu syekh menambahkan awalah sayid di tanda tangan mereka, juga pada
papan nama di rumah mereka. Penggunaan gelar secara main-main ini sungguh
membuat berang golongan sayid. Tidak
puas dengan upaya Jamiyat Khair dalam membela status mereka, pada tahun 1928
mereka mendirikan organisasi sendiri, Rabitah al ‘Alawijah, Liga Keturunan
Nabi. Pada tahun 1931 golongan qabili
dari suku al Katsiri, yang secara umum sepakat dengan pandangan golongan masakin, tak ketinggalan membentuk
organisasi sendiri juga, al Jami’ah al Katsiriyah al Islahiyah. Perpecahan
organisasi Arab ini menimbulkan gelombang polemik baru. Rabitah mengirim petisi
kepada pemerintah kolonial guna memohon perlindungan terhadap gelar
turun-temurun dan surat kepada dua sultan Hadramaut berisi permintaan agar
menertibkan para pembangkang. Hanya Sultan al-Syihr dan Makalla yang memihak
mereka, sedangkan gubernur jenderal memilih bersikap netral. Kubu Ba ‘Alawi dan
Irsyadi sama-sama mencari dukungan ulama di Timur Tengah dan media massa Arab
internasional. Hampir seluruh ulama dan media menganggap sistem kelas impor
Hadrami itu anakronis dan tidak pada tempatnya di Hindia Belanda, tentu ini
artinya mendukung para Irsyadi (De Jonge 1991: 93-9).
Kontroversi itu berbuntut panjang. Wulaiti memecat para pekerja muwalad
mereka, sesama tetangga tidak bertegur sapa lagi, orang-orang yang
berseberangan saling menghindar di jalan. Beberapa kali, orang-orang di luar
Hadrami, seperti Husein Abdin dari Singapura dan al-Amoedi dari Ambon, berusaha
mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, tetapi selalu tanpa hasil. Para pemimpin
dari masing-masing pihak atau komunitas tidak datang, atau janji yang
disepakati tidak ditepati. Komunitas yang dulunya agak tertutup dan tampaknya
harmonis itu berubah menjadi sebuah minoritas terbelah di mana masing-masing
pihak mencemooh lawannya secara terbuka. Situasi itu makin diperparah oleh
fakta bahwa Batavia, bersama Surabaya, adalah pusat jaringan komunikasi
komunitas Arab yang tersebar di seluruh Hindia Belanda. Setiap insiden di mana
saja akan membangkitkan kegemparan di Batavia, sementara setiap keputusan yang
dibuat di markas besar di ibu kota menambah keruwetan di mana-mana.
Pada tahun 1930-an perselisihan itu perlahan-lahan tampil
dalam karakter lain. Bukan konflik antara sayid
dan syekh lagi, persoalannya bergeser
menjadi sengketa antara wulaiti dan muwalad, antara generasi muda dan
generasi tua, dan antara pria dan wanita. Inti perdebatannya bukan lagi
privilese dan praktik-praktik Ba ‘Alawi, tetapi kedudukan komunitas Arab dalam
masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka yang lahir dan besar di Hindia
Belanda menyadari bahwa masa depan mereka bukan lagi di Hadramaut melainkan di
Indonesia. Oleh karena itu berbagai perubahan dalam tatanan tradisional tak
bisa dihindari. Tiga peristiwa mempercepat perubahan. Dalam sebuah kongres
Rabitah di Pekalongan yang membahas soal gelar, pada awal 1934, para anggota
muda, menimbulkan amarah golongan Arab totok tua, berhasil menghapus topik itu
dari agenda dan mengalihkan perhatian pada berbagai persoalan lain yang lebih
penting seperti modernisasi sistem sekolah. Pada akhir tahun itu juga, 39 anak
muda progresif peranakan Arab dari semua kubu, termasuk wakil Arab pertama di
Volksraad, Abdullah al-Attas, mendirikan Persatoean Arab Indonesia. Organisasi
yang menghendaki penyingkiran berbagai hambatan sosial tradisioanl dan
mendorong integrasi komunitas Arab ke dalam masyarakat Indonesia. Untuk pertama
kalinya, orang Arab berani mengatakan – mulanya agak ragu-ragu, tetapi kemudian
kian lantang – bahwa mereka sudah menjadi orang Indonesia. Sebuah sandiwara
berjudul Fatimah (putri Nabi dan ibu Husein, sayid pertama) mengundang luapan respons. Sandiwara itu mengangkat
isu-isu mutakhir dalam komunitas Arab, seperti kedudukan timpang perempuan dan
praktik riba kaum wulaiti (Algadri
1984: 161-3). Walaupun rasa permusuhan dalam komunitas sama sekali belum padam,
khususnya di Batavia yang secara tradisional banyak menampung wulaiti berlatar belakang sayid, segera menjadi jelas bahwa
komunitas Arab yang relatif tertutup sudah tidak ada.
Dipetik dari Huub De Jonge Sebuah Minoritas Terbelah: Orang Arab Batavia, dalam Jakarta Batavia: esai sosio kultural,
penyunting: Kees Grijns dan Peter J.M. Nas, penerjemah: Gita Widya Laksmini dan
Noor Cholis, Banana, KITLV, Jakarta, 2007.

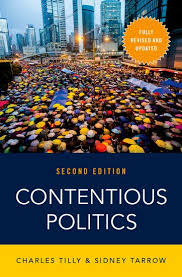

Comments
Post a Comment