Rumah Jagal Lima (terjemahan Slaughterhouse-Five) Saya sudah merampungkan buku perang saya sekarang. Yang akan saya tulis berikutnya pasti menyenangkan. Yang satu ini gagal, itu pasti, karena ia ditulis oleh patung garam. Ia berawal begini: Dengarlah: Billy Pilgrim melayang dalam waktu. Ia berakhir begini: Tuit-tuu-wiit? [ ... ] Begitulah bunyi akhir Bab Satu novel Rumah Jagal Lima ( Slaughterhouse-Five ). Benar, Kurt Vonnegut gagal, gagal menghasilkan karya yang buruk. Tidak hanya menjadi novel paling bagus Vonnegut dan salah satu buku terpenting yang pernah ditulis sejak 1945, ketika orang menyebut suatu karya termasuk kategori “Vonnegutian” yang mereka rujuk adalah Slaughterhouse-Five . Meskipun banyak orang mengenal karya satir yang lahir dari pengalaman ditawan di Dresden ini dengan or Slaughterhouse-Five , sesungguhnya judul lengkapnya adalah Slaughterhouse-Five or The Children’s Crusade, a Duty-dance with Death . Berkisah tentang pengalaman Billy...
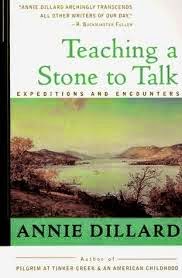
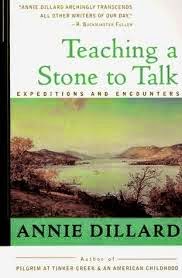
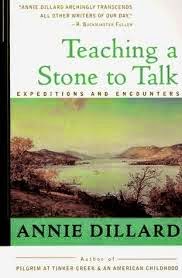
Comments
Post a Comment