PENYANGKALAN DAN REALITAS
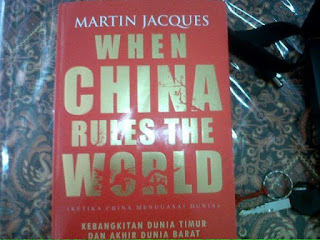 |
| When China Rules The World, Martin Jacques |
Pernyataan bahwa rasisme lumrah adanya dalam
masyarakat Cina disambut dengan semacam penyangkalan bernada marah, seolah-olah
itu adalah penghinaan terhadap bangsa Cina. Dalam sebuah perdebatan sangat
menarik—dan sangat tidak lazim—antara orang-orang Malaysia-Cina di sebuah
website Malaysia yang dipicu seorang penulis yang menyerang rasisme Cina, salah
seorang peserta membalas: “[klaim] bahwa rasisme adalah salah satu unsur
peradaban 5.000 tahun Cina adalah kebodohan dan menyebarkan pernyataan tak
berdasar semacam itu kepada orang-orang non-Cina dan kawan-kawan Cina yang
tidak membaca literatur klasik Cina adalah perbuatan berbahaya.” Yang lainnya
menanggapi: “Orang Cina dianiaya dan menjadi korban rasisme di seluruh dunia.
Tentunya kita tidak memerlukan rekan segolongan kita menuduh kita rasis.”
Pandangan standar orang Cina menyatakan bahwa
mereka sama sekali tidak rasis, bahwa rasisme pada dasarnya adalah apa yang
menimpa orang Cina dalam masyarakat Barat dan masyarakat Cina bisa dikatakan
tidak terjangkit rasisme. Sekadar menyebut satu dari sekian banyak contoh, pada
tahun 1988 Sekretaris Jenderal Partai Komunis saat itu, Zhao Ziyang, mengemukakan
dalam sebuah rapat tentang persatuan nasional bahwa diskriminasi rasial itu
lumrah “di mana-mana kecuali di Cina.”
Merasuknya rasisme tidak hanya bisa dijumpai di
Cina, melainkan juga Taiwan, Singapura, Hong Kong, bahkan dalam komunitas Cina
perantauan. Jadi, itu bukan cuma buah dari parokialisme atau kontak terbatas
Cina dengan dunia luar. Ambil sebagai contoh Hong Kong yang, bertolak belakang
dengan Cina, memiliki sejarah sangat kosmopolitan karena penjajahan. Walaupun
pada tahun 2001 Tung Chee-hwa, kepala eksekutif Hong Kong saat itu, biasa
menyebut rasisme sebagai masalah enteng, cuma diperlukan sedikit anggaran dan
kampanye pendidikan secukupnya, sesungguhnya rasime adalah endemi di kalangan
orang-orang Cina Hong Kong, yang merupakan 96 persen dari keseluruhan penduduk.
Dalam sebuah survei terhadap orang-orang Asia Tenggara, Asia Selatan dan Afrika
di Hong Kong yang dilakukan oleh Society of Community Organizations pada
tahun 2001, sekitar sepertiga responden mengatakan mereka ditolak bekerja
karena etnis mereka, proporsi yang sama mengatakan tidak boleh menyewa sebuah
flat, sepertiga dari mereka mengatakan bahwa polisi mendiskriminasikan mereka
di jalanan, sedangkan hampir separuh pernah mengalami diskriminasi rasial di
rumah sakit. Sasaran paling empuk adalah para “pembantu rumah tangga” asing,
lazim disebut “babu”, terutama warga negara Filipina dan Indonesia, yang sering
disuruh majikan Cina mereka bekerja lembur dengan jam kerja sangat kelewatan,
diperlakukan sangat buruk, dibayar murah, tidak diberi cukup kebebasan dan,
dalam sejumlah kasus kecil namun signifikan, mengalami siksaan dan pelecehan
seksual. Kondisi mereka tidak jarang menyerupai budak zaman dahulu, sesuatu
yang juga terjadi di Singapura dan Malaysia.
Rasanya wajar mengatakan bahwa rasisme orang Cina
Hong Kong adalah warisan Inggris. Setelah menguasai koloni menyusul Perang
Candu Pertama, Inggris menerapkan rasisme sistemik: bahasa Inggris dijadikan
sebagai satu-satunya bahasa resmi hingga 1974, orang Cina dilarang tinggal di
kawasan eksklusif Peak sejak 1902, diberlakukan bermacam-macam peraturan
apartheid untuk urusan-urusan sepele—seperti, hingga tahun 1897, kewajiban orang
Cina membawa surat jalan—dan mereka tidak bisa menduduki jabatan tinggi
pemerintahan hingga akhir 1970-an bahkan, di beberapa departemen, sampai
pertengahan 1990-an. Dengan mengabaikan habis-habisan kebenaran, pada tahun
1994 Inggris enteng saja mengatakan, “diskriminasi rasial di Hong Kong bukan
persoalan.” Fakta bahwa rasisme adalah mata uang pemerintahan Inggris mendorong
orang Cina untuk berperilaku sama terhadap yang mereka anggap lebih rendah dari
mereka, yakni orang-orang berkulit gelap. Tetapi naif tentunya menganggap bahwa
perilaku Inggris adalah penyebab utama sikap rasis orang Cina: tentu saja perilaku
itu adalah faktor penyubur tetapi alasan mendasarnya sendiri terletak pada
sejarah dan budaya Cina. Setelah kampanye besar menyusul tewasnya Harinder
Veriah, warga Malaysia keturunan India, yang mengeluhkan diskriminasi rasial
serius di sebuah rumah sakit Hong Kong pada tahun 2000, akhirnya pemerintah
terpaksa mengakui bahwa rasisme memang problem serius dan pada tahun 2008,
terutama berkat kasus ini, dengan sangat terlambat mereka mengesahkan
undang-undang anti-rasis untuk pertama kalinya. Tetapi Hong Kong, walaupun
kosmopolitan dan internasional, pada dasarnya tetap merupakan kota birasial, di
mana golongan kulit putih menikmati status istimewa, bersama orang Cina,
sementara mereka yang berkulit gelap dipinggirkan sebagai warga kelas dua atau
pekerja migran.
Lalu bagaimana rasisme di Cina sendiri? Ketika sebuah bangsa atau pemerintah menyangkal
rasisme mereka sendiri, bukti-bukti rasisme tersebut ada pada kesaksian mereka
yang menjadi korban dan, oleh karena itu, lebih banyak berbentuk anekdot
ketimbang apa saja yang lebih sistematis. Ketika budaya antirasisme—yang bertolak
belakang dengan budaya rasisme, seperti yang berlaku di Cina, Taiwan dan Hong
Kong—sudah mapan maka mungkin menyajikan
gambaran lebih akurat frekuensi kejadian rasis, sekalipun masih sangat banyak
yang tetap tersembunyi. Dalam masyarakat Cina, dan negara Cina khususnya, tidak
ada budaya antirasisme kecuali jauh di pinggiran karena wacana dominan
sauvinisme Han tidak sungguh-sungguh digugat. Sikap rasis dianggap normal
saja dan bisa diterima, bukan sesuatu yang abnormal dan patut ditolak. M. Dujon
Johnson, sarjana kulit hitam Amerika ahli Cina, mengatakan:
“Dalam
masyarakat Cina salah satu alasan jarang dibicarakannya secara terbuka isu ras
dan rasisme ... adalah karena rasisme diterima dan dibenarkan secara luas ....
Rasisme adalah ... isu yang tidak
dipersoalkan oleh orang Cina karena sebagaian besar dari mereka menganggap diri
lebih unggul dari orang berkulit gelap. Sehingga dalam pola pikir orang Cina
sungguh membuang-buang waktu mempersoalkan sebuah fakta gamblang tentang
inferioritas orang berkulit gelap.”
Dalam persepsi orang Cina terdapat sebuah hierarki
rasial sangat tegas. Orang kulit putih dihormati, disanjung dan diperlakukan
dengan sangat sopan oleh orang Cina; sebaliknya, kulit gelap dianggap buruk dan
dihinakan, makin gelap warna kulit makin buruk reaksinya. Orang-orang dari
negara-negara Asia Timur lain, yang secara tradisional dianggap lebih rendah,
bukan perkecualian. Seorang perempuan asal Filipina teman saya yang belajar di
Universitas Beijing terpana mendapati kadar diskriminasi yang dia alami. Tidak
seperti rekan-rekan kulit putihnya, yang diperlakukan dengan hormat, dia sering
dianggap tidak ada di restoran, para pelayan tidak mau melayaninya. Dia biasa
mendengar warga Cina setempat menyebutnya “bodoh” atau ‘dungu’. Dia pernah
tidak boleh naik bus oleh kondektur dengan isyarat yang menunjukkan bahwa dia
mengidap penyakit yang bisa menulari penumpang lain. Setelah dipermalukan di
depan umum seperti itu dia tidak mau naik bus. Dujon Johnson, yang pernah
melakukan survei tentang pengalaman orang-orang kulit hitam Amerika dan Afrika
di Cina dan Taiwan dengan mewawancarai mereka, mengatakan bahwa orang sering
pindah tempat duduk ketika ada orang kulit hitam duduk di samping mereka dalam angkutan
umum, atau menggosok-gosok bagian tubuh yang tersenggol orang kulit hitam di
keramaian, seolah-olah bagian tubuh itu perlu dibersihkan. Yang paling
menyedihkan, para responden Afrika menunjukkan bahwa mereka berusaha sebisa
mungkin menghindari kontak dengan khalayak Cina dan “biasanya hanya keluar jika
perlu.”
Diskriminasi terhadap mahasiswa Afrika di Cina
punya sejarah panjang. Emmanuel Hevi, orang Ghana yang belajar di Cina pada
awal 1960-an, mengatakan, “Setiap berurusan dengan kami orang Cina berperilaku
seolah-olah sedang berurusan dengan orang yang tidak punya kecerdasan normal.” Pada
Desember 1988, menyusul sebuah insiden antara mahasiswa Cina dan Afrika di
Universitas Heihai di Nanjing, 3.000 lebih mahasiswa Cina berpawai memprotes
keberadaan mahasiswa Afrika, demonstrasi itu kemudian merembet ke Shanghai,
Beijing dan tempat-tempat lain. Dalam beberapa demonstrasi iklimnya begitu
membahayakan mahasiswa Afrika sampai-sampai sejumlah universitas memutuskan
untuk memindahkan mereka dari asrama karena kemungkinan buruk terhadap
keselamatan fisik mereka. Tidak ada upaya dari pihak berwenang untuk
menghentikan atau mencegah demonstrasi yang berlangsung berhari-hari itu, boleh
jadi ini menunjukkan bahwa para demonstran memperoleh dukungan diam-diam dari
pihak berwenang. Di Sekolah Tinggi Industri Wuhan mahasiswa menggelar aksi
menuntut agar “semua orang kulit hitam diusir dari Cina”. Menurut
Dujon Johnson, kerusuhan dan demonstrasi
rasial tahun 1998 itu sama sekali tidak unik: kejadian serupa
pernah terjadi di Shanghai pada tahun 1979 dan 1980, di Nanjing pada tahun
1979, 1980, 1988 dan 1989, dan di Beijing pada tahun 1982, 1983, 1984, 1985,
1987, 1988 dan 1989. Pada September 2007 dilaporkan bahwa sebuah kelompok yang
setidak-tidaknya terdiri atas dua puluh orang kulit hitam, termasuk mahasiswa,
wisatawan dan putra seorang diplomat Karibia, ditangkap sepasukan polisi
berseragam hitam-hitam di sebuah klub malam Beijing dan dipukuli habis-habisan. Seorang saksi
kulit putih Amerika mengatakan bahwa: “Dia belum pernah melihat kejadian
sebrutal itu. Darah berceceran di jalanan. Mereka memukuli setiap orang kulit
hitam yang terlihat.” Perlu diingat bahwa wajah hitam masih merupakan
pemandangan luar biasa langka di Cina: tahun 2006 dilaporkan ada 600 orang
Afrika di Beijing, 500 di Shanghai, 100 di Shenzhen, dan lebih dari 10.000
orang di Guangzhou (yang berpenduduk 12 juta jiwa), terutama sebagai akibat
dari meningkatnya perdagangan dengan Afrika. Sudah barang tentu tidak terbiasa
dengan orang kulit hitam untuk sebagiannya menjelaskan kecurigaan dan
ketidakpercayaan orang Cina, tetapi itu
pasti bukan penjelasan utama bagi rasisme yang berurat mengakar. Uraian Dujon
Johnson tentang pengalaman orang kulit hitam di Cina tidak menyinggung
pengalamannya sendiri kecuali pada bagian akhir ketika dia menulis,
“[pengalaman saya] sehari-hari menunjukkan kepada saya betapa kehidupan dalam
masyarakat Cina tersekat-sekat secara rasial dan dalam banyak aspek menyerupai
sebuah sistem apartheid rasial.”
Sebagai reaksi terhadap kunjungan Condoleezza
Rice, Menteri Luar Negeri AS, ke Beijing tahun 2005, membeludak kiriman pesan
rasis di banyak website nasionalis. Penulis kawakan Cina Liu Xiaobo tergerak
menulis untuk menyatakan protes:
“Saya
menelusuri artikel-artikel BBS [blog] tiga portal terbesar Cina tentang
kunjungan Rice ke enam negara ... Ambil Sina sebagai contoh. Saya membaca lebih
dari 800 artikel BBS ... pengulangan diabaikan, ada lebih dari 600 artikel.
Hampir 70 artikel di antaranya, atau sepersepuluh dari keseluruhan, mengusung
diskriminasi rasial ... Hanya ada dua yang bernada sopan, selebihnya sangat
memuakkan. Banyak yang mencaci Rice sebagai “sangat jelek” ... “terjelek di
dunia” ... “Saya tidak habis mengerti bagaimana bisa umat manusia melahirkan
perempuan seperti Rice” ... Ada yang terang-terangan menyebut Rice “hantu
hitam”, “babi hitam” ... “tukang sihir” ... “sampah umat manusia” ... Ada juga
yang menyatakan kekecewaan: IQ orang Amerika rendah—bisa-bisanya mereka
mengangkat “sundal hitam” sebagai menteri luar negeri ... Tentu saja tidak ada
yang lupa untuk menggelari Rice dengan [nama-nama] binatang: “simpanse”,
“seperti burung”, “buaya”, “daging busuk”, “kotoran tikus”, [sesuatu] yang
anjing saja tidak doyan.”
Akhirnya, pemerintah Cina merasa perlu menutup blog-blog
itu dan beberapa situs.
Gelombang pasang nasionalisme rakyat pada akhir
1990-an, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai buku The China That Can Say
No, reaksi mahasiswa terhadap pengeboman Amerika Serikat atas Kedutaan
Besar Cina di Belgrade, dan banjir bah nasionalis di berbagai website
terkemuka, juga memuat dimensi rasial signifikan. Salah satu penulis nasionalis
paling berpengaruh adalah Wang Xiaodong, yang ikut menulis buku China’s Path
under the Shadow of Globalization, terbit tahun 1999 dan menjadi salah satu
buku laris. Wang berpendapat bahwa bangkitnya nasionalisme Cina
merepresentasikan langkah sehat kembali ke keadaan normal sesudah fenomena
abnormal yang disebutnya “rasisme terbalik” era 1980-an—“pemikiran bahwa budaya
Cina adalah inferior dan masyarakat Cina adalah ras inferior”—ketika, masih
menurut Wang, banyak intelektual Cina berkiblat ke Amerika Serikat untuk
mencari inspirasi dan menjelek-jelekkan budaya sendiri. Anehnya, Wang
berpendapat bahwa rasisme terbalik semacam itu “tidak jauh bedanya dari rasisme
Hitler,” pernyataan yang menunjukkan bahwa pandangannya tentang apa itu rasisme
sangat ajaib dan dia tidak tahu banyak soal Naziisme.
Wang menyatakan, dalam sebuah artikel yang terbit
setelah pengeboman kedutaan 1999, bahwa konflik antara Cina dan Amerika Serikat
tak terhindarkan karena bermotif rasial: di mata orang Amerika dan Eropa Barat,
orang “oriental” itu rendah, dan dia memperkirakan bahwa “isu ras akan semakin
sensitif seiring perkembangan sains biologi.”
“Amerika
Serikat bisa saja membuat senjata genetis yang ampuh untuk menumpas
kelompok-kelompok radikal yang secara rasial berbeda dari orang Amerika dan
yang melancarkan aksi terorisme terhadap Amerika Serikat. Karena secara genetis
jauh lebih mudah membedakan orang Cina dari orang Amerika ketimbang membedakan
orang Serbia dari orang Amerika, sangat boleh jadi senjata genetis yang
membidik orang Cina lebih dulu dibikin.”
Dalam nada yang sama, Ding Xueliang, sarjana Cina
yang tinggal di Hong Kong, menyatakan bahwa perbedaan rasial dan budaya antara
Amerika Serikat dan Cina, berikut perbedaan sistem poluitik dan kapasitas
nasional, menyebabkan Amerika Serikat akan memandang Cina sebagai musuh besar.
Contoh-contoh tersebut mengingatkan bahwa ras tetap merupakan faktor
berpengaruh dalam pemikiran Cina dan menopang sebagian besar sentimen
nasionalis.
Dari Martin Jacques, When China Rules The World: The Rise Of The Middle
Kingdom And The End Of The Western World, Allen Lane an imprint of Penguin
Books, subjudul asli Denial And Reality
h. 256 - 261. |
| Martin Jacques' Work, source of picture www.penguin.co.uk
Untuk versi yang sudah disunting dan, tentu saja, lebih baik silakan baca
bukunya
Judul : When China Rules The World Ketika
China Menguasai Dunia; Kebangkitan Dunia
Timur dan Akhir Dunia Barat.
Penerjemah : Noor Cholis (penyelia), Jarot Sumarwoto.
Penerbit : Penerbit Buku Kompas 2011
|



Comments
Post a Comment