Ekspedisi Kutub (5) - TAMAT
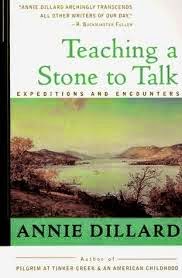 |
| Annie Dillard's Teaching a Stone to Talk |
Teknologi
Pada abad
kesembilan belas, seseorang menyimpulkan keberadaan Antartika.
Sepanjang
kurun itu, tidak seorang pun di bumi ini yang bisa memastikan ada
tidaknya daratan di selatan, walaupun seorang Amerika bernama Charles
Wilkes menyatakan pernah melihatnya. Beberapa ahli geografi dan
penjelajah berpsekulasi bahwa di sana tidak ada daratan, yang ada
cuma Lautan Antartika beku; sedangkan sebagian yang lainnya
mengasumsikan adanya dua pulau besar di sekitar Kutub. Bahwa di sana
ada sebuah benua, itu baru ditetapkan pada tahun 1935.
Pada tahun
1893, seseorang yang bernama John Murray di hadapan Perhimpunan
Geografi Kerajaan menyampaikan sebuah deduksi tentang benua
Antartika. Kapal ekspedisinya, Challenger,
tidak
pernah terlihat di benua semacam itu. Deduksinya dikembangkan
sepenuhnya dari aktivitas pengerukan dan pengukuran kedalaman
perairan dengan suara. Dalam uraiannya dia memaparkan sebuah benua
besar, sebuah peta spekulatif yang dia bikin. Dia mendeskripsikan
dengan akurat topologi benua tak dikenal itu: plato sentral berikut
sistem tekanan tinggi permanennya, gletser luar biasanya yang
menghadap ke Laut Selatan, deretan pegunungan vulkaniknya di satu
pantai, dan di pantai yang lain, deretan dataran rendah dan
perbukitan. Dia benar.
Dengan
demikian deduksi adalah sesuatu yang mungkin—walaupun sudah tidak
mode lagi. Ada banyak teknik yang mungkin dipakai untuk eksplorasi
daerah kutub. Misalnya, ada yang namanya ekspedisi menghanyut.
Ketika
sepasang celana kedap air kuning milik awak Jeannette
yang hilang itu muncul tiga tahun kemudian di Greenland, setelah
hilang di utara Rusia tengah, penjelajah Norwegia Fridtjof Nansen pun
tertarik. Berdasarkan perjalanan celana itu dia menyusun
noktah-noktah di peta kemungkinan arah arus di basin kutub. Kemudian
dia melakukan sebuah ekspedisi menghanyut: pada tahun 1893 dia
sengaja mengarahkan kapalnya, Fram,
ke pulau es apung dan membuang sauh menunggu saat arus bergerak ke
utara dan, dia berharap, menuju ke Kutub. Selama hampir dua tahun,
dia dan dua belas awaknya hidup di kapal saat lautan beku membawa
mereka. Nansen menulis dalam buku hariannya, “Aku rindu kembali ke
kehidupan . . . tahun-tahun berlalu di sini . . . Oh! Kadang-kadang
berdiam diri begini meremukkan jiwa orang; hidup orang tampak sama
gelapnya dengan malam musim dingin di luar; tidak ada sinar matahari
yang menjamahnya kecuali pada masa lalu dan masa depannya yang jauh,
sangat jauh. Aku merasa seolah-olah aku harus
menerobos keadaan mati ini.”
Karena arus
tidak membawa mereka ke Kutub, Nansen dan seorang awaknya bertolak
pada suatu musim semi membawa kereta anjing dan kayak ke Kutub
berjalan kaki. Keadaan memang sangat ganas di dataran es itu, hingga
setelah mencapai garis lintang utara yang sudah tercatat, keduanya
berbalik ke selatan menuju daratan, menghabiskan musim dingin bersama
di sebuah pondok batu di Kepulauan Frans Josef dan hidup dengan
mengandalkan daging beruang kutub. Musim semi berikutnya mereka
kembali, setelah hampir tiga tahun, ke peradaban.
Ekspedisi
Nansen adalah yang pertama dari sekian ekspedisi menghanyut. Semasa
Perang Dunia I, para anggota ekspedisi Arktik Kanada berkemah di atas
lempeng es apung seluas tujuh mil kali lima belas mil; mereka
menghanyut selama enam bulan sejauh empat ratus mil di Laut Beaufort.
Pada tahun 1937, sebuah pesawat terbang menurunkan sebuah ekspedisi
menghanyut Rusia di atas lempeng es apung di dekat Kutub Utara.
Keempat ilmuwan Soviet itu menghanyut selama sembilan bulan sementara
lempeng es apung mereka, membentur es daratan, berulang kali terpecah
menjadi bagian yang makin kecil.
Daratan
Aku, lihatlah,
berangkat lagi.
Hari-hari
bertemu banyak makna. Sudut-sudut ditimbuni puisi; seluruh sistem
yang tidak tuntas mengotori es.
Teknologi
Seorang letnan
bernama Maxwell, anggota ekspedisi kutub kedua Vitus Bering, menulis,
“Kau tidak akan merasa aman ketika harus melayari perairan yang
benar-benar kosong.”
Para ahli peta
menyebut ruang kosong di peta sebagai “putri tidur”.
Di atas
peta-peta kami aku melihat simbol-simbol untuk perairan dangkal dan
di sampingnya terdapat tulisan “P. D.” Teman dudukku di bangku
gereja, si kikuk berkumis yang berpengalaman dengan peta navigasi dan
paham bagaimana menentukan posisi berdasarkan bintang-bintang,
memberitahuku bahwa inisial itu adalah kependekan dari “Position
Doubtful”, Posisi Meragukan.
Daratan
Untuk
mengetahui lokasi pasti Kutub, pilihlah suatu malam gelap dan jernih
untuk memulai. Dengan navigasi biasa tetapkan lokasi Kutub di sebuah
area seluas beberapa yard
persegi. Lalu pasang di atas es di area itu serangkaian kamera.
Arahkan kamera-kamera itu ke titik tertinggi langit; biarkan bukaan
kamera-kamera itu terbuka. Lalu cuci film. Film dari kamera yang
ditempatkan tepat di Kutub akan menunjukkan bintang-bintang malam
yang berputar sesempurna lingkaran-lingkaran konsentris sirkular.
Teknologi
Aku menyukai
kesendirian, juga senyap, dan apa yang disebut Plotinus “kepergian
sendiri menuju Sendiri.” Aku menyukai kesendirian. Sir John
Franklin, nampaknya, menyukai backgammon.
Apakah yang semacam itu sesuai dengan kondisi?
Anda
meninggalkan rumah dan negeri Anda, meninggalkan kapal Anda, juga
meninggalkan teman-teman Anda di tenda, seraya berkata, “Aku akan
keluar, mungkin agak lama.” Cahaya di tepi jauh badai es memikat
Anda. Anda berjalan, dan suatu hari memasuki jantung terbentang
senyap, di mana daratan lenyap dan lautan menjadi uap serta es
menyublim di bawah bintang-bintang tak dikenal. Inilah akhir Via
Negativa, tepi tanpa cahaya di mana tebing pengetahuan memudar, dan
cinta demi cinta itu sendiri, tanpa objek, bermula.
Daratan
Kukenakan
senyap dan menunggu. Kutinggalkan kapal dan berangkat berjalan kaki
ke es kutub. Aku membawa kronometer dan sekstan, tenda, kompor dan
bahan bakar, daging dan lemak. Untuk air aku melelehkan es yang
kucacah-cacah dengan kapak kecil; air asin beku rasanya tawar. Aku
tidur ketika tidak sanggup lagi berjalan. Aku berjalan mengikuti
kompas yang menunjuk utara geografis.
Aku berjalan
dalam hampa; aku mendengar napasku. Aku melihat tangan dan kompasku,
melihat es yang begitu luas melengkung, melihat puncak planet ini
membentuk kurva dan atmosfer rendahnya terus menurun. Tahun-tahun
berlalu di sini. Aku sedang berjalan, seringan sejumput aurora; aku
seringan layar, setumpuk garis-garis tak berwarna; aku berteriak
“langit dan bumi tidak bisa dibedakan!” dan arus di bawah kaki
membawaku dan aku berjalan.
Badai salju
seperti selembar tabir; aku memasukinya. Salju yang menerpa menempel
di mataku. Tidak ada yang bisa dilihat atau diketahui. Aku menunggu
di tenda, diriku hanyut dan tidak berbuat apa-apa, selama
berminggu-minggu saat badai menggila. Suatu hari segalanya berakhir,
kubereskan tenda dan berjalan. Badai menjernihkan udara; gerombolan
awan tersingkir; matahari berputar-putar di langit seperti seekor
ikan dalam mangkuk bundar, seperti sebutir kerikil menggelinding
dalam ember, seperti perenang, atau sebuah melodi menghentak
berulang-ulang, terus berulang di atas di segala penjuru.
Namaku Senyap.
Senyap adalah bivakku, dan makan malamku kuseruput dari mangkuk. Tiap
pagi aku mengenakan untaian longgar batu-batu. Mataku adalah batu;
sepotong es memenuhi mulutku. Tengkorakku adalah basin kutub;
tempurung otakku menumbuhkan gletser, dan gunung es, dan es melumer,
dan lempeng es apung. Tahun-tahun sedang berlalu di sini.
Jauh di depan
adalah perairan bebas. Aku tidak tahu sedang musim apa, tetapi tahu
berapa lama aku berjalan ke dalam kesenyapan seperti sebuah
terowongan yang melebar di depanku, ke dalam tangan terentang
cakrawala yang meluas laksana air. Aku berjalan menuju pinggir pulau
es apung, menuju tepi yang melepas lempeng-lempengnya ke air hijau
dan hitam; aku berdiri di pinggir dan melihat ke atas. Bercak-bercak
lelehan es di kulit air sejauh bisa kulihat menggores laut dan
tercerai-berai tiap kali sebongkah es atau salju timbul tenggelam
atau mengapung lewat. Lempeng-lempeng es apung tampak tebal di air,
beberapa di antaranya sebesar pulau. Di sampingku sedang lewat sebuah
panci datar lempeng es apung dan di atasnya seseorang mengulurkan
dayung. Kupegangi sirip dayung itu dan melompat. Aku mendarat di atas
lempeng es apung panjang.
Tak seorang
pun berbicara. Di sini, di haluan lempeng es apung, badut-badut
meriah itu mengikatkan diri di es. Dengan patok tenda dan tali mereka
mengikatkan pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka ke lempeng
es apung itu di mana mereka berbaring telentang dan diam, menatap ke
atas. Di antara para badut, juga terikat, terdapat anak-anak
laki-laki dan gadis kecil, beberapa perempuan, dan beberapa laki-laki
dari berbagai negara. Salah seorang dari para laki-laki itu adalah
Nansen, penjelajah Norwegia yang menghanyut. Salah seorang perempuan
berulang-ulang membuka dan mengepalkan tinjunya. Salah seorang badut
menyibak jumbai lehernya, memperlihatkan kulitnya. Berjam-jam aku
melewati orang-orang yang terikat itu, bermaksud kembali lagi nanti
dan mengambil tempatku.
Melangkah
lebih jauh aku melihat pastor tinggi itu juga ada di situ, pastor
yang menyajikan bagi komuni jus anggur pada sebuah kebaktian ekumenis
beberapa tahun yang lalu, di negara lain. Dia sudah tua sekali.
Sendiri di atas sebidang salju yang dihempas angin dia berlutut,
berdiri, dan berlutut, dan berdiri, dan berlutut. Tak jauh darinya,
di tepi lempeng es apung, duduk di atas peti kemas, adalah si pembuat
deduksi John Murray. Dia menurunkan bandulan pengukur kedalamannya
dari kapal dan mengulur tali. Dia mengenakan topi bulu antik Doctor
Akal, seperti yang dipakai Erasmus dalam potret; dimaklumi bahwa
andai dia kembali dan memaparkan temuan-temuannya, dia pasti jadi
bahan tertawaan, karena topinya itu. Kapten Oates anak buah Scott
juga ada; dia tidak punya kaki. Orang inilah yang keluar dari
tendanya,
demi menyelamatkan teman-temannya. Kini di atas kehormatannya dia
berdiri dan menyiapkan tali kendali layar linen; dia melangkahi
tiang kayu di tengah kapal bukit.
Dari buritan
lempeng es apung itu rasanya aku mendengar musik; aku beranjak,
tetapi aku membutuhkan beberapa tidur untuk sampai ke situ. Aku tidak
lagi menggunakan tenda. Setiap kali bangun, aku mengamati lempeng es
apung itu dan cakrawala lautan mencari tanda—tanda-tanda pulau es
apung yang kami tinggalkan, atau tanda-tanda perairan bebas, atau
daratan, atau sembarang cuaca. Tidak ada yang berubah; hanya ada laut
hijau dan es mengapung, dan laut hitam di kejauhan bertabur gunung
es, dan angin buritan ajek yang beraroma garam mineral tak dikenal,
dan dasar lautan.
Akhirnya aku
mencapai buritan luas lempeng es apung itu, pantai sangat
centang-perenangnya, kerumunan orangnya, unggunan api memasaknya. Ada
anak-anak yang menggendong bayi, para laki-laki dan perempuan yang
melukisi kulit mereka dan mencoba menangkap bayang-bayang mereka di
air dan menyimpannya di tempat terlindung. Di dekat tepi air terdapat
sebuah piano kayu, sebuah bangku dengan buku telepon di atasnya.
Seorang perempuan sedang duduk di atas buku telepon itu dan memainkan
lagu Sanctus. Angin bertambah kencang. Aku menyanyi keras-keras,
sekadar berkelakar.
Banyak badut
di sini; salah seorang di antaranya membagi-bagikan kue-kue Pandu
Putri, kue-kue itu lengket menyatu. Belum lama berselang, aku baru
tahu, Sir John Franklin dan awaknya naik lempeng es apung ini, begitu
pula anak buah kapal Polaris
dan
Jeannette
yang
hilang. Mereka, yang seragam kunonya mengundang pandangan iri,
kelaparan. Sebagian dari mereka mulai berlaku kasar terhadap si
mesdinar bengal. Seorang anak buah kapal memanggul anak itu menyusuri
tepi lempeng es menghampiri piano, di mana dia meninggalkan anak itu
demi segenggam kue dan tempat duduk di bangku di sebelah si pianis
pendek, yang kaki tak beralasnya, mungkin karena buku telepon itu,
tidak bisa menjangkau pedal. Dia mulai memainkan “The Sound of
Music.” “Anda tahu Bach tidak?” aku bertanya pada perempuan
itu, yang kakinya tampak sangat sibuk dengan kaki anak buah kapal
kelaparan itu; “Anda tahu Mozart tidak? Atau mungkin ‘How Great
Thou Art’?” Seorang perwira kurus kering yang mengenakan syal
sutra hitam menemukan Laksamana Peary, yang dapat dikenali dari
kejauhan berkat bendera aneh di tangannya. Peary dan perwira itu
bersama-sama merencanakan sebuah pertunjukan amatir dan drama komedi
pendek. Ketika mereka mendekatiku, aku menawarkan diri untuk
menyanyikan “Antonio Spangonio, The Bum Toreador” dan/atau
membaca sepenggal fiksi pendek; mereka mengatakan akan memberi tahu
aku nanti.
Kristus,
menyangka bahwa kami semua adalah penguin, berpose jongkok di depan
kamera. Dia jongkok, dalam jubahnya, di antara penyanyi utama
Wildflowers,
yang dengan riang berusaha menentukan sudut terbaik untuk memegang
gitarnya di depan kamera, dan istri si petani, yang terus menatap
jari kakinya yang dilukisi sampai si ayah baptis Filipina yang
menangani kamera berseru “Cheese.”
Perempuan bergaya country
itu, bernyanyi-nyanyi, berhasil menjejalkan sepotong kue kepada si
bayi Oswaldo. Bayi Oswaldo berdiri dalam jubah berenda dan sepatu
tenis birunya di tengah lingkaran para penjelajah, membuat kesal
mereka.
Di tanganku
kudapati sebuah tamborin. Di depan sejauh cakrawala yang rapuh, aku
melihat gunung-gunung es di antara lempengan es apung. Aku melihat
gunung-gunung es dan lempeng-lempeng gunung es berkolom-kolom dan
retakan gelap di air di antara mereka. Menggantung di bawah balutan
awan menebal adalah garis-garis tak berwarna gelap yang memantulkan
genangan perairan terbuka di kejauhan. Aku mengayun-ayunkan tamborin,
dan menyanyikan apa pun yang dimainkan pemain piano; saat ini lagunya
“On Top of Old Smoky.” Aku mengayun-ayunkan tamborin dan
menyanyikan lagu itu keras-keras hingga semua orang menyingkir.
Tetapi siapa yang bisa memelankannya? Sebab kami sedang mendekati
Kutub.
Dalam kenangan
Gayuh Utami Nugroho, semoga Allah memudahkan urusannya. Diterjemahkan
dari Annie Dillard, An
Expedition to the Pole
dalam Teaching
a Stone to Talk,
HarperPerennial, 1992, h. 29 – 64.



Comments
Post a Comment