Pasang Surut Hubungan Asia Tenggara dan Cina
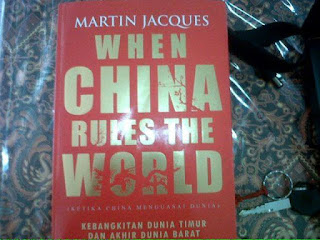 |
| When Chine Rules The Wolrd, Martin Jacques |
[ ... ]
Karena faktor geografis, secara tradisional
negara-negara kepulauan Asia Tenggara relatif lebih renggang hubungan mereka
dengan Cina daripada Myanmar dan Vietnam yang satu daratan dengan Cina. Lebih
jauh, perbedaan etnis, budaya dan agama antara Cina dan negara-negara seperti
Malaysia dan Indonesia juga sangat jelas. Malaysia, menyusul kemerdekaannya
pada tahun 1957, menaruh kecurigaan besar terhadap Cina karena warga negara
keturunan Cinanya yang berjumlah besar dan fakta bahwa pemerintahan Mao
mendukung perang gerilya, yang basis utamanya adalah etnis Cina setempat,
melawan Inggris dan, sesudah kemerdekaan, melawan pemerintah baru yang
didominasi orang Melayu. Berkat pertumbuhan pesat ekonomi Cina selama periode
reformasi, berikut keputusan Cina berhenti menganjurkan perubahan revolusioner
di negara lain, hubungan kedua negara terus membaik. Walaupun bertikai soal
Kepulauan Spratly, Perdana Menteri Malaysia saat itu Mahathir Mohamad memilih
politik bertetangga baik dengan Cina, paham betul negaranya tidak akan bakal
menang dalam bentrok angkatan laut. Mahathir juga memainkan peran penting
selama satu dekade lebih dalam mendorong Cina agar lebih terlibat di kawasan
itu dan khususnya dengan ASEAN.
Dalam jangka panjang setiap peningkatan hubungan
dengan Cina tampaknya mempengaruhi perimbangan rasial genting di Malaysia
antara mayoritas Melayu dengan dan minoritas Cina, yang kini mencapai lebih
dari seperempat jumlah keseluruhan penduduk. Tidak mengherankan, kelompok minoritas
inilah yang lebih banyak terlibat perdagangan dengan Cina, yang memenuhi
penerbangan antara kedua negara, dan yang paling diuntungkan secara ekonomi
dari hubungan bilateral tersebut. Oleh sebab itu Malaysia, walaupun
mengupayakan hubungan lebih dekat dengan Cina, pasti akan tetap agak ambivalen.
(Problem kuatnya minoritas Cina secara ekonomi tidak terbatas di Malaysia saja:
minoritas Cina, walaupun relatif lebih kecil daripada di Malaysia, juga
memainkan peran dominan dalam sektor swasta di Thailand, Indonesia, Myanmar,
Laos, Kamboja, Vietnam dan Filipina.)
[ .... ]
Secara historis, sistem upeti adalah pelengkap
internasional identitas dan eksistensi Cina sebagai sebuah negara-peradaban.
Dan persis seperti pengaruh negara-peradaban tetap terlihat jelas dalam ranah
domestik, keawetan sistem upati tampak pula dalam ranah hubungan internasional.
Bahkan dalam hal-hal penting sekalipun sikap Cina terhadap konsep-konsep
kedaulatan dan hubungan antarnegara terus mengandalkan warisan sistem upeti
sama seperti sistem Westphalian kontemporer. Konsep kedaulatan Cina sangat
berbeda dari yang dipahami dalam hukum internasional model Barat. Ambil sebagai
contoh sengketa atas kedaulatan kepulauan Spratly dan Paracel, yang, walaupun
sekarang dikesampingkan—menyusul perjanjian dengan ASEAN—dalam jangka panjang
belum akan selesai. Nyaris tidak bisa disebut kepulauan, sebetulnya kepulauan
Spratly dan Paracel adalah gugusan karang tak berpenghuni, sebagian besar di
antaranya lebih banyak berada di bawah permukaan laut, di Laut Cina Selatan,
Spratly terletak di sebelah utara Malaysia Timur dan sebelah barat Filipina,
sedangkan Paracel berada di sebelah timur Vietnam.
Ide tentang kedaulatan maritim adalah kreasi yang
relatif baru, lahir pada tahun 1945 ketika Amerika Serikat menyatakan niat
untuk menegaskan kedaulatan di wilayah
perairannya, dan inilah sesungguhnya yang menjadi dasar klaim berbagai negara
Asia Tenggara atas kepulauan Spratly dan Paracel. Cina, sebaliknya, mendasarkan
argumennya pada “klaim-klaim historis’, yakni bahwa kepulauan tersebut selama
ribuan tahun menjadi bagian tak terpisahkan dari perbatasan tenggara Kerajaan
Tengah sama halnya dengan, misalnya, perbatasan daratan di utara Beijing.
Berbagai ekspedisi ke kepulauan itu menemukan bermacam-macam artefak Cina, seperti
keramik Cina dan uang tembaga dari dinasti Tang dan Song, yang dipakai menopang
“klaim-klaim historis” tersebut dan membuktikan bahwa kepulauan itu sudah lama
merupakan bagian dari Cina. Kepulauan tersebut adalah bagian dari folklor
budaya Cina, yang dihidup-hidupkan, dalam berbagai kutipan semangat pionir
Cina, oleh artikel-artikel yang ditulis para jurnalis Cina yang rutin
mengunjungi kepulauan tersebut. Kepulauan itu dimuat dalam peta-peta Cina
sejelas dalam “garis klaim historis” dan dengan demikian merupakan bagian dari
Cina. Pulau Hainan, di lepas pantai selatan Cina, boleh jadi adalah provinsi
daratan terkecil Cina, juga dianggap—karena luas wilayah maritimnya,
sebagaimana diklaim, mencapai Laut Cina Selatan—sebagai “provinsi lautan”
terbesarnya. Pada tahun 2007, Beijing membentuk kota praja baru Sansha di
Provinsi Hainan, dengan yurisdiksi mencakupi tiga pulau kecil yang diklaim
Vietnam di kepulauan Spratly dan Paracel. Tindakan itu menyulut demonstrasi
besar-besaran di kedutaan besar Cina di Hanoi. Pemikiran tentang “klaim
historis” mendapat tempat dalam penggunaan hukum antarwaktu Cina, yang
mengurusi benar atau salah dalam masa lalu historis. Para ahli hukum Cina
berpendapat bahwa: “sebuah fakta yuridis harus ditimbang menurut hukum-hukum pada
masanya, bukan menurut hukum yang berlaku ketika perselisihan timbul.” Pendapat
memberi kekuatan dan legitimasi lebih kepada sejarah ketimbang masa kini,
kepada hukum yang berlaku pada masa sistem upeti dan bukan sistem hukum
internasional mutakhir.
Pada tahun 1984 Deng Xiaoping mengemukakan
“kemungkinan menyelesaikan sengketa teritorial tertentu dengan mengajak
negara-negara yang terlibat untuk bersama-sama membangun wilayah sengketa
sebelum membicarakan masalah kedaulatan.” Dengan kata lain, masalah kedaulatan
jangan sampai menghambat perkembangan isu-isu lain. Pernyataan Deng ini sering
dikutip oleh sumber-sumber Cina dalam konteks kepulauan di Laut Cina Selatan,
di mana pendekatannya itu dalam praktiknya diikuti, dan berkenaan dengan
kepulauan Diaoyu/Senkaku di Laut Cina Timur yang disengketakan dengan Jepang;
pernyataan itu juga disarankan sehubungan dengan Taiwan. Walaupun berkukuh
dalam soal kedaulatan atas Taiwan, Cina menawarkan untuk menyampingkan masalah
itu hingga tempo yang bisa dikatakan tak tertentu, asalkan Taiwan tidak
menyatakan kemerdekaan, memperlibatkan kelenturan yang dipersiapkan Cina dalam
mengatasi iu tersebut. Atau kalau tidak begitu, mereka mengatakan bahwa,
asalkan kedaulatan mereka atas pulau itu diakui rakyat Taiwan, Taiwan boleh
terus mempunyai pemerintahan, sistem politik, bahkan angkatan bersenjata
sendiri.
Ini menyoroti perbedaan fundamental lain antara
konsep kedaulatan Cina dengan yang dianut di Barat—terlihat paling jelas dalam
sikap yang ditunjukkan Cina terhadap penyerahan kedaulatan di Hong Kong. Bagi
pihak Cina pengalihan kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar, seperti halnya
dalam semua kasus yang disebut wilayah yang hilang—yaitu Taiwan, Hong Kong,
Macao dan boleh jadi juga berbagai kepulauan yang disengketakan—yang dianggap
Cina, berdasarkan sejarah, budaya dan etnis, sebagai kepunyaannya. Tetapi
menurut standar Barat kedaulatan itu ditegakkan dalam cara yang kelewat lentur.
Narasi Inggris—dan Barat—mengenai Hong Kong adalah, menyusul penyerahan pada
tahun 1997, Cina akan mengubah wilayah itu menjadi sesuatu yang sangat mirip
dengan Cina daratan. Perkiraan yang meleset. Secara keseluruhan, Hong Kong
tidak banyak berubah. Bisa dikatakan hal itu sungguh tidak lumrah dalam
transisi pasca-kolonial. Kunci untuk memahami langkah Cina terletak pada
pengertian “satu negara, dua sistem”, sebagaimana tertuang dalam konstitusi
wilayah itu, atau yang dikenal juga sebagai Hukum Dasar. Bagi Cina, yang
penting adalah pengakuan kedaulatannya atas Hong Kong dan bukan apakah wilayah itu
akan menganut sistem pemerintahan yang sama atau tidak. Pendekatan Barat
berbeda: kedaulatan dan sistem tunggal adalah sinonim. “Satu negara, dua
sistem” mengakara dalam tradisi ribuan tahun Cina yang mengakui dan menerima
bermacam-macam perbedaan di banyak provinsinya atau, boleh dibilang,
perbedaan-perbedaan semacam itu merupakan bagian yang inheren dan mutlak
diperlukan dari sebuah negara-peradaban. Dengan kata lain, negara-peradaban,
seperti sistem upeti turunannya, didasarkan pada prinsip “satu peradaban,
banyak sistem.” Sebaliknya, pengertian kedaulatan Barat bersandar pada prinsip
“satu negara, satu sistem”, dan sistem Wesphalian bertumpu pada “satu sistem,
banyak negara-bangsa”.
Sikap Cina menyangkut kedaulatan terkait erat
dengan konsep lama Konfusian “harmoni dengan perbedaan”, yang dihidupkan
kembali di bawah pemimpin Cina saat ini, Hu Jiantao. Bahkan beberapa sarjana
Cina menafsirkan “satu negara,dua sistem” sebagai contoh dari “harmoni dengan
perbedaan”. Jika dalam wacana Barat, harmoni menyiratkan identitas dan afinitas
erat, tidak demikian halnya dalam tradisi Cina, yang memandang perbedaan
sebagai karakteristik hakiki harmoni. Menurut Konfusius, “orang yang menjadi
panutan selaras dengan orang lain, tetapi tidak harus setuju dengan mereka; orang
kecil setuju dengan orang lain tetapi tidak selaras dengan mereka.” Menyetujui
orang berarti Anda tidak kritis seperti mereka: lawan harmoni bukan
kekacaubalauan melainkan keseragaman dan homogenitas. Menariknya, di Cina
homogenitas sering dikaitkan dengan istilah “hegemoni”, yang dipakai secara
peyoratif untuk menggambarkan perilaku kekuasaan besar—dulu Uni Soviet,
sekarang Cina—kebalikan dari “harmoni” yang dipandangkan memungkinkan dan
menerima perubahan.
Dalam membicarakan hubungan masa depan Cina dan
tetangga-tetangganya di Asia Timurnya, penting untuk tidak hanya
memperhitungkan warisan historis sistem upeti melainkan juga apa yang bisa
disebut realpolitik ukuran. Tentunya ini adalah aspek signifikan sistem
upeti merupakan faktor makin menentukan dalam era globalisasi dan negara-bangsa
modern. Cina sangat ingin menegaskan keinginannya untuk menahan diri dan
menghormati kepentingan negara-negara lain, tetapi dalam jangka panjang, dengan
asumsi Cina melanjutkan kebangkitan ekonominya, disparitas antara Cina dan
negara-negara di kawasan itu akan mencolok seiring waktu. Tidak sulit untuk
membayangkan sebuah skenario di mana ketimpangan antara kekuatan Cina dan
kekuatan negara-negara tetangganya akan lebih besar daripada yang bisa ditemui
di kawasan lain dunia. Kekuatan yang
begitu besar itu akan terungkap dalam beragam cara, mulai dari ekonomi dan
budaya, hingga politik dan militer. Inilah faktor utama di balik kecurigaan
laten negara-negara di kawasan tersebut terhadap Cina: yang ditakutkan bukan
Cina sekarang—apalagi ketika ia bersemangat untuk meyakinkan
tetangga-tetangganya—tetapi akan seperti apa ia nantinya. Pada tahun 1996
panglima angkatan laut Malaysia mengatakan: “seiring waktu berlalu, muncul ...
ketidakpastian menyangkut perilaku Cina begitu ia menyandang status kekuatan
besar. Apakah ia akan mengindahkan aturan-aturan internasional atau regional,
apakah ia akan menjadi kekuatan militer baru yang bertindak sekehendaknya?
Bayangkan hubungan lima puluh tahun ke depan antara Cina yang kuat dan maju
dengan penduduk lebih dari 1,5 miliar, dengan Laos atau Kamboja yang pada saat
itu penduduknya mungkin mencapai sekitar 10 juta dan 20 juta; atau boleh juga
Malaysia, dengan penduduk lebih dari 30. Berdasarkan ukuran—apalagi warisan
sistem upeti—hubungan antara Cina dan kawasannya berbeda secara mendasar dari
hubungan antara negara dominan dengan negara-negara tetangganya di kawasan
lain.
Akan seperti apa Cina? Bagaimana ia akan
bertindak? Jelas bahwa perilaku Cina terhadap, dan konsepsinya tentang, kawasan
itu sangat dipengaruhi oleh warisan sistem upeti dan karakternya sebagai
negara-peradaban. Pengaruh cara berpikir ini sudah terlihat dalam sikap Cina
terhadap kepulauan Spratly dan Paracel, Hong Kong dan Taiwan.
Setidak-tidaknya di kawasannya sendiri, bisa
dinyatakan sebagai tegas bahwa Cina tidak akan sekadar menjadi sebuah
negara-bangsa Westphalian. Taruhlah demikian,
akan sekuat apa Cina nanti? Apakah perilaku Cina di masa depan harus
dinilai dengan sikap menahan diri dan tindakan relatif mulia yang merupakan
karakteristik rezim saat ini, ataukah hal itu akan ditenggelamnkan oleh sesuatu
yang lebih Sinosentris? Dapatkah perlahan-lahan Cina meninggalkan sikap ekstra
hati-hatinya saat ini dan menjadi lebih galak terhadap negara-negara yang,
misalnya India, Jepang dan negara-negara Asia Tenggara, terlibat sengketa
wilayah dengan Cina dan Cina sepakat untuk mendiamkannya saat ini? Ketika
bertambah kuat, tidak mengherankan jika Cina menjadi semakin Sinosentris:
sesungguhnya, setidak-tidaknya dalam jangka panjang, memang itulah yang
diperkirakan. Bagaimanapun juga, penekanan sangat kuat saat ini pada
pembangunan ekonomi dan keinginan untuk memastikan tidak ada gangguan, sikap
menahan diri untuk sebagiannya bisa dikatakan merupakan prioritas: pada era reformasi,
disiplin diri Cina sangat hebat dan mengesankan. Tetapi memikirkan masa depan
ketika standar hidup jauh lebih tinggi dan Cina memantapkan diri sebagai
kekuatan dominan di Asia Timur, bagaimana kira-kira sebuah pandangan yang lebih
Sinosentris memanifestasikan diri?
Barangkali cara terbaik menjawab pertanyaan ini
adalah mencari petunjuk-petunjuk yang ada saat ini, betapapun langka dan
samarnya. Ada tiga contoh. Yang pertama adalah invasi Cina ke Vietnam pada
Februari 1979, yang dibuat Cina sebagai “perang hukuman untuk memberi pelajaran
Vietnam” tentang dekatnya Cina dan keyakinannya bahwa Vietnam tidak tahu terima
kasih atas bantuan Cina selama Perang Vietnam. Bahasa perang itu, nada pongah
imperial, hasrat untuk meneguhkan hubungan hierarkis, perlunya saudara tua
memberi pelajaran adiknya, berasal dari zaman tata dunia Cina pramodern dan
sistem upeti. Dalam corak tidak berbeda, Cina menggunakan kekuatan
militer dalam sengketa kepulauan di Laut Cina Selatan, terhadap Filipina pada tahun 1995 dan terutama
sekali terhadap Vietnam pada tahun 1956, 1974, dan diulangi lagi pada tahun
1988, ketika Cina merebut enam pulau di area Spratly, tiga kapal Vietnam
ditenggelamkan dan 72 kelasi Vietnam tewas. Aksi-aksi tersebut ini
bercorak sistem upeti, kehendak untuk meneguhkan tatanan hierarkis segala
sesuatu dan, kalau perlu, menghukum mereka yang coba-coba melenceng. Tetapi
perlu diketahui bahwa hubungan Cina dan Vietnam sudah jauh membaik dalam
beberapa tahun terakhir, walaupun kebencian di antara mereka, yang sudah
berabad-abad umurnya, mengakar sangat dalam.
Contoh yang kedua adalah hubungan Cina dan warga
negaranya di luar negeri. Akhir 2005 beredar dugaan bahwa seorang turis
perempuan Cina di Malaysia digeledah telanjang dan dilecehkan pihak berwajib
Malaysia. Isu itu diberitakan pertama kali oleh China Press, surat kabar
Malaysia berbahasa Cina, dan selanjutnya diangkat begitu gegap gempita oleh
media Cina sampai-sampai perdana menteri Malaysia memerintahkan penyelidikan
independen, menginstruksikan menteri dalam negeri untuk melakukan lawatan
khusus ke Beijing guna menjelaskan dan meminta maaf. Sebuah tajuk di Harian
Cina, surat kabar resmi
pemerintah, berseru: “Siapa saja yang berotak waras pasti tersentak oleh
foto-foto perempuan setanah air kita dipaksa “jongkok memegangi telinga” dalam
keadaan telanjang oleh seorang polisi
wanita Malaysia berseragam. Tidak ada dalih yang bisa membenarkan kebrutalan
sengawur itu.” Tajuk itu tidak cukup menahan diri atau hati-hati. Celakanya tak
lama kemudian ketahuan perempuan yang dimaksud ternyata bukan warga negara
Cina, orang Cina pun bukan. Itu perempuan Melayu. Respons Cina terhadap insiden
itu, sejak awal, tidak proporsional dan agresif, dan didasarkan pada informasi
salah yang dipungut pers Malaysia-Cina. Tentu saja keliru menarik kesimpulan
terlalu banyak dari satu insiden saja, tetapi reaksi Cina itu, dalam situasi
demikian, arogan dan meledak-ledak. Cina memperlakukan pemerintah Malaysia tanpa sopan
santun. Mereka bahkan tidak memperimbangkan untuk memeriksa fakta-faktanya
terlebih dahulu. Mereka bertindak dengan gaya imperial terhadap apa yang
tampaknya mereka anggap, setidak-tidaknya demikian kesannya, sebagai negara
tidak penting. Sementara itu, pemerintah Malaysia sendiri bertindak layaknya
negara pembayar upeti yang sudah semestinya merendah dan menghormat. Dengan
pariwisata Cina yang maju pesat di kawasan itu, insiden tersebut menunjukkan
bahwa perlindungan terhadap warga negara Cina di luar negeri akan sangat
diperhatikan dan proaktif sekurang-kurangnya, menyerang dan agresif pada titik
puncaknya.
Contoh terakhir adalah reaksi rakyat Cina terhadap
kerusuhan yang menimpa warga keturunan Cina di Indonesia pada tahun 1997. Pada
saat itu pemerintah Chian menunjukkan sikap menahan diri, berusaha mencegah
demonstrasi yang dilancarkan orang-orang Cina perantauan di Hong Kong, Taiwan,
New York, Asia Tenggara dan Australia. Tak urung, dilihat dari tulisan-tulisan
di internet, reaksi kebanyakan orang Cina adalah kemarahan. Berikut adalah
salah satu contoh:
Ibu pertiwi, kaudengarkah tangis itu? Anak-anakmu
di negeri orang menjerit. Tolong mereka. Aku tidak mengerti politik dan tidak
berani bicara politik. Aku tidak tahu apa artinya mengatakan “kita tidak punya
teman atau musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi”, dan aku tidak
tahu apa kepentingan itu ... yang kutahu hanyalah saudara-saudara sebangsaku
dibantai dengan brutal, mereka butuh pertolongan, bukan cuma pernyataan
memahami dan keprihatinan moral. Ibu pertiwi, mereka adalah anak-anakmu. Darah
di tubuh mereka adalah darah ras Han. Ketulusan dan itikad mereka juga tumbuh
dari asuhanmu. Tolonglah ....
Walaupun marak sentimen-sentimen demikian, pemerintah Cina bertindak dengan
hati-hati dan wajar; tetapi ketika kekuatan Cina di kawasan itu meningkat,
hubungan antara Cina dan orang Cina perantauan—yang menguasai kekuatan ekonomi
luar biasa di hampir semua negara ASEAN, dan yang rasa percaya diri, status dan
posisinya akan banyak terangkat berkat kebangkitan Cina—akan menjadi faktor
yang semakin penting di negara-negara itu. Ditopang oleh kebangkitan Cina,
warga keturunan Cina setempat boleh jadi berusaha memanfaatkan meningkatnya
posisi tawar mereka guna menambah kekuatan mereka, sementara pemerintah di
negara-negara itu kemungkinan akan semakin berhati-hati dalam menyikapi
kelompok minoritas Cina mereka karena takut membuat Beijing marah. Sejarawan
Gungwu menyatakan bahwa orang-orang Cina perantauan mempunyai banyak kesamaan
karakteristik dengan kelompok-kelompok etnis minoritas lain: “Tetapi yang
membuat orang “Cina”’ sangat berbeda adalah “ibu pertiwi” di dekat Asia
Tenggara, sangat besar dan padat, berpotensi berpengaruh besar dan secara
tradisional memandang rendah bangsa dan budaya lain di kawasan itu.”
Untuk versi yang sudah disunting dan, tentu saja, lebih baik silakan baca
bukunya
Judul : When China Rules The World Ketika
China Menguasai Dunia; Kebangkitan Dunia
Timur dan Akhir Dunia Barat.
Penerjemah : Noor Cholis (penyelia), Jarot Sumarwoto.
Penerbit : Penerbit Buku Kompas 2011



Comments
Post a Comment