Cina dan Ras
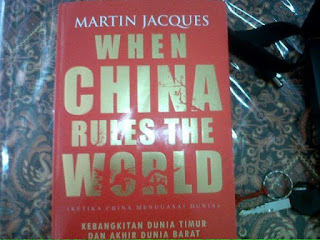 |
| When China Rules The World, Martin Jacques |
Rasisme adalah subjek yang orang sering berusaha
menghindarinya, dianggap terlalu tidak mengenakkan secara politis, sekadar
menyebutkan keberadaannya saja sering mengundang reaksi amarah meledak-ledak
dan penolakan mentah-mentah. Padahal rasisme sangat penting bagi wacana
sebagian besar, kalau bukan seluruh,
masyarakat. Ia selalu mengintai di suatu tempat, kadang-kadang di permukaan,
kadang-kadang di bawahnya. Ini juga tidak mengherankan. Manusia memandang diri sehubungan dengan kelompok,
dan perbedaan fisik adalah penanda yang jelas dan tegas dari berbagai kelompok.
Sekadar untuk memudahkan saja jika orang menghubungkan karakteristik kultural
dan mental dengan suatu kelompok berdasarkan perbedaan-perbedaan fisik
kasatmata: dengan kata lain, untuk merumuskan secara esensial
perbedaan-perbedaan fisik itu, menambatkan budaya pada alam, untuk menyamakan
kelompok-kelompok sosial dengan unit-unit biologis. Terdapat sebuah pandangan
yang dianut luas, terutama di Asia Timur, bahwa rasisme adalah “problem orang
kulit putih”: itulah yang dilakukan orang kulit putih terhadap pihak lain. Di
Cina maupun Taiwan, pendirian resmi menyatakan bahwa rasisme adalah sebuah
fenomena budaya Barat, sedangkan Hong Kong menganut pandangan yang umumnya
sama. Omong kosong. Semua orang berkecenderungan pada cara berpikir semacam
itu—atau, dengan kata lain, semua ras memupuk prasangka rasial, menerapkan mode
berpikir rasis dan mempraktikkan rasisme terhadap ras lain. Bahkan, rasisme
adalah sebuah fenomena universal dan tidak ada ras perkecualian, bahkan mereka
yang sangat menderita karenanya. Tetapi setiap rasisme, walaupun mempunyai
karakteristik yang sama dengan rasisme lainnya, juga khas, dibentuk oleh
sejarah dan budaya suatu bangsa. Persis
seperti ada banyak budaya berbeda-beda, ada banyak rasisme yang berbeda-beda.
Rasisme kulit putih membawa dampak jauh lebih besar dan lebih mendalam—serta
merusak—bagi dunia modern ketimbang rasisme lain mana pun. Karena orang kulit
putih memiliki kekuasaan jauh lebih besar ketimbang kelompok rasial lain mana
pun dalam dua abad terakhir, pengaruh mereka—dan prasangka mereka—menjangkau
lebih jauh dan berdampak lebih besar, terutama berkat kolonialisme. Bukan berarti
bangsa-bangsa lain tidak mempunyai sikap dan prasangka serupa terhadap ras-ras
yang mereka anggap lebih rendah.
Ini jelas berlaku di Asia Timur. Walaupun jarang
diakui, di banyak bagian kawasan itu, terutama Asia Timur Laut, pengertian
identitas sangat kental dengan gagasan rasial. Banyak istilah di Cina dan Jepang
sejak akhir abad kesembilan belas yang menyatakan bahwa kedua negara itu adalah
entitas yang khas secara biologis. Di Cina istilah tersebut meliputi zu (silsilah/marga),
zhong (benih, tunas, jenis, ras), zulei (jenis silsilah), minzu
(silsilah suku bangsa, kebangsaan, ras), zhongzu (anakan silsilah, jenis
silsilah, anakan, ras), renzhong (anakan manusia, manusia), sedangkan di
Jepang mencakupi jinshu (anakan
manusia, anak manusia), shuzoku (anakan silsilah, jenis silsilah,
anakan, ras) dan minzoku (silsilah suku bangsa, kebangsaan, ras). Bahkan
di Asia Tenggara, yang jauh lebih heterogen secara rasial, identitas rasial
tetap sangat kuat. Singkatnya, rasa kepemilikan bermotif rasial kental sering
terletak di jantung identitas nasional di Asia Timur.
Pentingnya wacana rasial di Cina dan masyarakat
Konfusian lain seperti Jepang, Singapura, Taiwan, Korea dan Vietnam menimbulkan
pertanyaan mengapa bisa demikian halnya. Jawabannya hampir pasti terkait dengan
posisi sentral keluarga, yang merupakan jalinan tak putus dan krusial dalam
tradisi Cina (maupun semua masyarakat Konfusian lainnya) dan yang, bersama
negara, merupakan lembaga kemasyarakatan utama. Keluarga menentukan makna
primer “kita”, tetapi keluarga juga terkait erat dengan ide tentang silsilah,
yang berfungsi menentukan “kita” yang jauh lebih besar. Orang di Cina sudah
lama terbiasa menganggap orang lain yang bernama sama berarti punya leluhur
sama. Sejak dinasti Ming, berbagai silsilah berlainan dengan nama keluarga yang
sama lazim menghubung-hubungkan leluhur dan menjalin hubungan kekerabatan
fiktif melalui sosok historis terkenal, misalnya Kaisar Kuning. “Seluruh
penduduk Cina,” kata Kai-wing Chow, “bisa dibayangkan sebagai sebuah himpunan
silsilah, karena mereka semua punya nama keluarga Han yang sama.” Dan
kenyataan bahwa relatif tidak banyak nama keluarga di Cina semakin memperkuat
efek ini. Dalam adat istiadat Cina, silsilah, seperti halnya keluarga, erat dikaitkan dengan
kesinambungan biologis dan garis darah (sebuah gagasan yang mendapatkan signifikansi
kultural mendasar dalam masyarakat Konfusian) sebagaimana, pada akhirnya,
bangsa itu sendiri. Ini tercermin dalam pengertian tentang kewarganegaraan, di
mana darah merupakan prakondisi yang menentukan dalam masyarakat-masyarakat
tersebut: bahkan hampir mustahil mendapatkan kewarganegaraan dengan cara selain
itu.
Sama sekali bukan ciptaan Barat, rasisme mempunyai
akar purba di Cina maupun Jepang. Bukti tertulis dari, sekurang-kurangnya,
tahun 1000 SM yang dikutip Jared Diamond memperlihatkan bahwa orang Cina
menganggap diri lebih unggul dari orang non-Cina dan orang Cina utara
menganggap rekan mereka di selatan sebagai orang barbar. Di Cina kuno, elite
berkuasa mengukur berbagai kelompok dengan sebuah standar budaya yang
menentukan bahwa siapa saja yang tidak mengikuti tata cara Cina dianggap
barbar, walaupun orang barbar tersebut nantinya bisa digolongkan ulang
tergantung kadar asimilasinya. Di Kerajaan Tengah, kaum barbar umumnya dibagi
menjadi dua kategori: “barbar mentah” (shengfan) yang dianggap biadab dan melawan, dan “barbar matang” (shufan)
yang dianggap sebagai jinak dan patuh). Kaum barbar matang dianggap berada di
titik dapat diadabkan, barbar mentah tidak bisa diapa-apakan. Mereka yang hidup
di luar perbatasan Cina dianggap sebagai barbar mentah atau, lebih parah, mirip
binatang. Perbedaan antara manusia dan hewan kabur dalam folklor Cina,
kelompok-kelompok asing yang hidup di luar Cina sering dianggap sebagai
orang-orang biadab yang berdekatan dengan kebinatangan dan sering disebut dengan
penggunaan radikal-radikal binatang (radikal adalah komponen utama dari aksara
Cina), dengan demikian mengidentifikasi orang-orang non-Cina yang berlainan
dengan berbagai jenis binatang. Dari sini jelas bahwa rasa unggul masyarakat
Cina didasarkan pada sebuah kombinasi budaya dan ras—keduanya terjalin tak
terpisahkan, arti penting relatif masing-masing bervariasi menurut zaman dan
keadaan. Frank Dikötter, yang menulis kajian utama dalam bahasa Inggris tentang
rasisme Cina, mengemukakan:
“Di satu
sisi, klaim tentang universalisme budaya mendorong golongan elite menegaskan
bahwa orang-orang barbar dapat “di-Cina-kan”, atau diubah dengan pengaruh
positif budaya dan iklim. Di sisi lain, ketika rasa superioritas budaya Cina
terancam, para elite menyerukan perbedaan-perbedaan kategoris alamiah untuk
mengusir kaum barbar dan menutup negara dari pengaruh menyesatkan dunia luar.”
Meski begitu, pandangan ekspansif lebih sering
berlaku ketimbang defensif.
Warna kulit adalah yang mula-mula dianggap
penting. Sejak zaman paling kuno, orang Cina memilih untuk menyebut diri
berkulit putih, kulit cerah sangat dihargai dan disamakan dengan giok putih. Pada
awal abad kedua belas, golongan elite menyandangkan nilai tinggi pada orang
berkulit putih, dan kesadaran mengenai warna kulit di kalangan elite menjadi
sesuatu yang sensitif karena kontak maritim yang dijalin pada masa dinasti Song
Selatan (1127-1279 M). Dalam periode itu bahkan citra Buddha yang baru populer
diubah dari seorang “India berkulit gelap setengah telanjang menjadi orang suci
berpakaian lebih pantas dengan kulit terang”, persis seperti Yesus dibikin
putih dalam tradisi Kristen Barat. Tentu tidak semua orang Cina berkulit
terang. Mereka yang bekerja keras dan lama di sawah di bawah terik matahari
tentunya lekang dimakan cuaca dan berkulit gelap. Jadi jarak, dan perbedaan,
simbolis yang direpresentasikan oleh kelas dan tampak jelas pada warna kulit
diproyeksikan oleh golongan elite Cina ke dunia luar ketika mereka makin sering
berhubungan dengan suku bangsa dan ras lain. Kulit putih dianggap sebagai pusat
dunia beradab, diwujudkan oleh Kerajaan Tengah, sedangkan hitam
merepresentasikan kutub negatif manusia, dilambangkan dengan bagian-bagian
terjauh dunia yang dikenal. Ketika orang Cina menjadi terbiasa dengan negeri-negeri
jauh pada masa dinasti Ming, terutama berkat pelayaran Cheng Ho ke Afrika dan
Asia Tenggara pada abad kelima belas, persepsi mereka tentang perbedaan warna
kulit dan fisik menjadi lebih berwarna-warni, orang Afrika dan aborigin selalu
ditempatkan di dasar, sedangkan orang Melayu dan Vietnam sedikit di atasnya.
Pada masa dinasti Qing, kategori rasial menjadi
faktor utama dan eksplisit dalam karakterisasi orang barbar. Hal ini
mencerminkan pergeseran penting dari norma-norma budaya yang sebelumnya
cenderung berlaku, walaupun unsur rasial selalu signifikan. Selanjutnya
taksonomi dan klasifikasi rasial baru dielaborasi, didorong oleh peperangan
dahsyat yang dilancarkan orang-orang Cina di wilayah barat, yang membuat mereka
berhubungan dengan orang-orang sangat berbeda dari mereka yang, di sepanjang
paruh kedua abad kesembilan belas, berusaha mereka tundukkan, tetapi hanya
berhasil sebagian. Tetapi semakin meningkatnya keberadaan dan kekuatan bangsa
Eropa menyusul Perang Candu, dan krisis kian parah yang dihadapi dinsti Qing
sebagai akibatnya, adalah pukulan paling telak dan menimbulkan perubahan
terbesar dalam sikap orang Cina, bukan cuma di kalangan elite melainkan juga
pada tataran populer. Sejak tahun 1890-an rasisme budaya Cina kuno diartikulasikan
dalam filsafat rasis baru populer oleh kalangan akademisi dan penulis, yang
dipengaruhi oleh teori-teori rasial dan Darwinisme yang berlaku di Barat saat
itu. Rasisme pun menjadi bagian tak terpisahkan dari cara pikir rakyat,
diartikulasikan dalam penerbitan yang diedarkan luas, terutama di antara
penduduk kota pelabuhan-pelabuhan traktat. Wacana rasial baru ini mencakupi
seluruh aspek perbedaan fisik, mulai
warna kulit dan rambut hingga tinggi badan, ukuran hidung, warna mata, ukuran
kaki dan bau badan: tidak ada yang luput dari perhatian, setiap detail fisik
ditelaah untuk mencari signifikansi mental dan kultural lebih luas. Orang-orang
barbar sudah disebut “setan” pada abad itu, tetapi belakangan mereka dibedakan
menurut warna kulit. Ras Kaukasian disebut “setan putih” (baigui) dan
mereka yang berkulit gelap adalah “setan hitam” (heigui),
sebutan-sebutan yang masih umum dipakai saat ini. Namun, setan-setan itu tidak
dipandang sama: setan putih dianggap “penguasa” dan setan hitam adalah “budak”.
Literatur-literatur tentang pelabuhan-pelabuhan traktat sarat dengan penghinaan
terhadap mereka yang berasal dari Afrika dan India.
Selama periode ini, bersamaan dengan makin
populernya istilah “Han”, orang Cina mulai menyebut diri sebagai ras kuning,
bukan putih, sebagai upaya membedakan diri dari orang Eropa di satu pihak dan
mereka yang berkulit lebih gelap di pihak lain. Ketika Cina berusaha melawan
ancaman Eropa yang semakin meningkat, dunia dilihat dalam pengertian
Darwinis-sosial survival of the fittest, mereka yang berkulit gelap
dianggap gagal dan oleh karena itu sudah nasib mereka untuk diabaikan,
sedangkan ras kuning, dipimpin oleh bangsa Cina, sedang bertempur sengit
melawan ras putih dominan. Kuning mempunyai konotasi sangat positif
di dunia Cina, mengingat keterkaitannya dengan Sungai Kuning dan Kaisar Kuning.
Pada tahun 1925 penyair Wen Yudio, yang pernah menetap di Amerika Serikat,
menulis puisi berjudul “Aku orang Cina” yang mengungkapkan gejolak rasa
nasionalisme rasialis Cina, yang dalam hal ini disangatkan pengalamannya di
Barat:
Aku orang Cina, aku orang Cina,
Akulah darah suci Kaisar Kuning,
Aku datang dari tempat tertinggi di dunia,
Pamir adalah tanah leluhurku,Rasku laksana Sungai Kuning,
Kami mengalir menuruni lereng pegunungan Kunlun,
Kami mengalir membelah benua Asia,
Dari kami mengalir tradisi luhur,
Bangsa agung! Bangsa agung!
Merebaknya cara berpikir rasialis digarisbawahi
oleh Frank Dikötter, yang mencatat contoh-contoh tak terbilang banyak, dengan
menambahkan:
“Keliru
mengasumsikan bahwa klise-klise ini dihimpun ... cukup menggunakan saringan
untuk memilah ungkapan-ungkapan rasial. Dibutuhkan kapal keruk untuk
mengumpulkan semua klise, stereotipe dan citra rasial yang melimpah ruah di
Cina (juga di Barat) dalam periode antarperang. Klise-klise ini adalah ciri
paling wacana rasial yang beredar luas dan sangat berpengaruh, juga jarang
dipersoalkan. Klise-klise ini diadopsi dan dilestarikan oleh sebagian besar
kaum intelektual.”
Di samping jelas-jelas merupakan produk situasi
makin memburuk Cina imperial, ungkapan sebuah krisis identitas serta hasrat
bagi peneguhan dan kepastian, rasisme tersebut juga merupakan buah dari rasisme
kultural yang menjadi ciri utama Kerajaan Langit selama kurun hampir tiga ribu
tahun. Ketatnya hierarki rasial yang kemudian menjadi endemik itu sangat mirip
dengan hierarki budaya tatanan sosial Konfusian—bagi hubungan timbal balik
rumit antara bentuk-bentuk superioritas kultural dan rasial dalam masyarakat
Cina.
Pemikiran rasialis ini sangat mempengaruhi kaum
nasionalis, di bawah pimpinan Sun Yat-sen, yang menumbangkan dinasti Qing dalam
Revolusi 1911. Sun memandang bangsa Cina sebagai satu ras dan meyakini
konfrontasi tak terelakkan antara ras kuning dengan putih:
“Umat
manusia terbagi ke dalam lima ras. Ras kuning dan putih relatif kuat dan
cerdas. Karena lemah dan bodoh, ras-ras yang lain dimusnahkan oleh ras putih.
Hanya ras kuning yang mampu bersaing dengan ras putih. Ini yang disebut evolusi ... di antara ras-ras
kontemporer yang bisa disebut superior hanyalah ras kuning dan putih. Cina
termasuk ras kuning.”
Di tempat lain dia menulis: “Kekuatan terbesar
adalah kesamaan darah. Bangsa Cina termasuk ras kuning karena mereka berasal
dari darah mulia ras kuning. Darah leluhur mengalir turun-temurun melalui ras
dan itu menjadikan kekerabatan sedarah sebagai kekuatan dahsyat.” Pada mulanya
dia menganggap sepi orang-orang Tibet, Mongol, Manchu dan lain-lain karena
jumlah mereka yang tidak berarti: dia nasionalis Han yang memandang bangsa Cina
melulu dalam bingkai Han, dan dengan demikian sebagai sebuah ras-bangsa. Tetapi setelah Revolusi
dia membentur realitas warisan Cina Qing di mana, walaupun jumlah mereka
mungkin kecil, etnis-etnis minoritas itu mendiami lebih dari separuh wilayah
Cina. Jika Cina didefiniskan hanya sehubungan dengan Han, pemerintah harus
menghadapi prospek pemberontakan etnis dan tuntutan kemerdekaan—dan, pada
akhirnya, memang itulah yang terjadi. Menghadapi situasi demikian pemerintahan
nsionalis Sun Yat-sen berubah haluan dan mendefinisikan ulang Cina dalam
bingkai satu ras dan lima kebangsaan, yakni Han, Manchu, Mongol, Tibet dan Hui:
dengan kata lain, Cina diakui sebagai sebuah negara multinasional, walaupun
cuma terdiri atas satu ras, semuanya mempunyai asal-usul Cina yang sama. Chiang
Kai-shek melanjutkan garis besar pendekatan ini, hanya saja dia menganut garis
yang sangat asimilasionis, menindas kelompok-kelompok etnis minoritas dengan
alasan mereka harus dipaksa mengadopsi adat istiadat dan praktik-praktik Han
secepat mungkin.
Revolusi 1949 mengawali sebuah pergeseran besar
dalam kebijakan. Wacana rasis yang marak sejak akhir abad kesembilan belas pun
secara resmi dilarang dan nasionalisme Han dibabat. Cina dinyatakan sebagai
negara kesatuan multi-etnis, walaupun pemerintah, setelah menawari sebentar
kelompok-kelompok etnis minoritas (disebut sebagai suku bangsa) hak untuk
menentukan nasib sendiri, segera menarik kembali tawaran itu. Mereka justru
mendorong kelompok-kelompok etnis minoritas untuk mengajukan permohonan bagi pengakuan
resmi status identitas etnis mereka, akhirnya lima puluh enam permohonan
dikabulkan (termasuk Han). Sifat
kelompok-kelompok itu sangat beragam: ada yang memiliki kesadaran identitas
etnis sangat kuat, ditambah dengan aspirasi separatis (orang-orang Uighur dan
Tibet), ada yang memiliki kesadaran
identitas etnis kuat dan awet tetapi tidak punya ambisi separatis (misalnya
orang Yi), ada pula yang kesadaran identitas etnisnya sangat lemah (seperti
orang Miao, Zhuang dan Manchu), sedangkan selebihnya, sisa-sisa dari masa
lampau sebelum kurang lebihnya mengalami asimilasi total dengan orang-orang
Han, hampir tidak ada kecuali dalam entri birokrsi (misalnya orang-orang Bai
dan Tujia). Kategori terakhir ini sesungguhnya merangkum sejarah arus utama Cina,
yaitu proses Hanifikasi pelan-pelan namun tak kenal henti. Kelompok-kelompok
etnis minoritas dengan identitas sangat kuat diberi semacam otonomi dengan
pembentukan lima daerah otonom (yaitu Daerah Otonom Mongolia Dalam, Xinjiang
Uighur, Guangxi Zhuang, Ningxia Hui dan Tibet, yang memiliki kekuasaan
terbatas, termasuk hak kelompok minoritas untuk menunjuk menteri utama; tetapi
pembentukan daerah-daerah otonom tersebut tidak pernah dimaksudkan sebagai
sarana yang bisa dipakai kelompok-kelompok etnis minoritas menjalankan semacam
pemerintahan otonom. Ada tiga kelompok etnis yang, selama abad kemarin, terus
memperlihatkan gerakan separatis serius, yakni Mongol, Tibet dan Uighur di
Provinsi Xinjiang. Orang-orang Tibet
menikmati otonomi relatif besar sebelum pendudukan Cina pada tahun 1951,
sedangkan Xinjiang, yang artinya “wilayah baru”, mengecap kemerdekaan sebentar
sebagai Turkistan Timur atau Uighurstan pada tahun 1933. Masing-masing daerah
tersebut menikmati status otonom; walaupun pada pelaksanaannya otonomi tersebut
dipangkas. Di Daerah Otonom Mongolia etnis Han empat kali lebih banyak dari
Mongol, membuat orang Mongol relatif tidak berkutik. Bahkan kampung halaman
para penakluk Cina zaman dahulu, Mongol dan Manchu, kini dipenuhi orang-orang
Han. Di Daerah Otonom Tibet, orang Han masih kalah banyak dari orang Tibet,
sedangkan di Xinjiang, daerah penghasil utama minyak dan gas Cina, mereka setidak-tidaknya
merupakan 40 persen dan mungkin lebih dari separuh, padahal menurut sensus
tahun 1950-an jumlah mereka hanya 6 persen dari total populasi. Masing-masing
daerah tersebut dengan demikian mengalami proses klasik berulang-ulang
pemukiman Han yang mengubah, dan pelan tapi pasti terus mengubah, perimbangan
etnis mereka. Maka tidak mengherankan bila hubungan antara orang-orang Han dan
Tibet, juga orang-orang Han dengan Uighur, yang mayoritas beragama Islam dan
menggunakan rumpun bahasa Turki, terus diliputi kecurigaan dan berjarak.
Dengan memangkas sauvisnisme Han, menghindari
klaim bahwa Han adalah inti Cina dan memberikan kesetaraan hukum sepenuhnya
bagi kelompok-kelompok etnis minoritas, pemerintah Komunis menyingkirkan ekses
terburuk asimilasi periode Nasionalis. Di bawah Mao, bahasa ras diganti dengan
bahasa kelas. Kendati demikian, sikap-sikap dasar Han tidak banyak berubah.
Terdapat prasangka mengakar di kalangan orang-orang Cina Han, termasuk mereka
yang berpendidikan tinggi, terhadap kelompok-kelompok etnis minoritas. Menurut
Stevan Harrel, seorang ahli tentang kelompok etnis minoritas Cina, terdapat “perasaan
unggul bawaan, nyaris naluriah, orang-orang Han.” Dia mencontohkan seorang
pejabat Han pada sebuah proyek kehutanan pemerintah di daerah Yi dan, walaupun
sudah tinggal di sana selama dua puluh tahun, tidak pernah mencoba makanan Yi
yang menurut dia kotor dan akan membuatnya sakit. Sama sekali tidak dianggap
setara, etnis minoritas dipandang rendah
karena kurang modern. Terdapat keyakinan mendasar bahwa mereka harus diangkat
ke derajat Han, yang budayanya dianggap sebagai model untuk diikuti dan ditiru
kelompok-kelompok minoritas. Budaya mereka diakui cuma menyangkut hal-hal
remeh, misalnya dalam pakaian tradisional dan tari-tarian, tetapi tidak
diperlakukan setara dengan golongan Han dalam masalah-masalah yang lebih
mendasar. Pada hakikatnya itu tidak berbeda jauh dari arogansi budaya Konfusian
yang dicangkokkan secara etnis dan mewarnasi era imperial. Walaupun menjadi
tidak begitu eksplisit setelah Revolusi 1949, cara pikir rasialis tidak pernah
lenyap, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari, walaupun tersamar, cara
pandang orang Cina dan sejak awal peiode reformasi cara pikir tersebut muncul
lagi dalam budaya populer maupun di lingkungan pemerintahan.
Dari Martin Jacques, When China Rules The World: The Rise Of The Middle
Kingdom And The End Of The Western World, Allen Lane an imprint of Penguin
Books, subjudul asli The Chinese and Race,
h. 244 – 252. Untuk versi yang disunting dan, tentu saja, lebih baik silakan baca buku
Judul : When China Rules The World Ketika
China Menguasai Dunia; Kebangkitan Dunia
Timur dan Akhir Dunia Barat.
Penerjemah : Noor Cholis (penyelia), Jarot Sumarwoto.
Penerbit : Penerbit Buku Kompas 2011



Comments
Post a Comment