Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung
Oleh: Daniel S. Lev
Ketika Presiden Soeharto melepaskan jabatannya di
bawah tekanan pada Mei tahun 1998, salah satu tuntutan yang paling gencar dan
lantang dilontarkan adalah reformasi hukum, secara sederhana berarti menjamin
proses hukum yang jujur, konsisten, dan bisa diperkirakan. Hal ini sesungguhnya
tidak baru. Sejak kejatuhan sistem parlementer dan tampilnya Demokrasi
Terpimpin, yang disusul dengan kudeta Orde Baru (Orba) 1965, penyesalan
terhadap merosotnya negara hukum—rechtsstaat
versi Indonesia—dan tuntutan agar ide itu dipulihkan, sudah kerap didengar, namun
diabaikan elite politik Indonesia.
Sesaat setelah Soeharto mundur, harapan akan reformasi
hukum menguat, terutama dari masyarakat yang sudah muak dengan hukum yang tak
berfungsi, advokat, akademisi, intelektual, hingga donor asing. Yang disebut
terakhir ini datang dengan pendekatan meyakinkan untuk membentuk aparat penegak
hukum, administrator, dan advokat yang lebih jujur dan kompeten, memberantas korupsi,
serta menempatkan semua orang sama di hadapan hukum dan lembaga hukum.
Kemarahan mahasiswa di jalanan, Organisasi non-Pemerintah (Ornop) reformis,
yang sebagian secara khusus mengagendakan reformasi hukum, dan begitu banyaknya
perhatian pers, menjadikan reformasi yang bersifat fundamental tampak niscaya,
meski sama sekali tidak gampang. Tekanan diarahkan pada pengadilan, kejaksaan,
kepolisian, profesi hukum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pengadilan-pengadilan niaga baru dibentuk dengan
bantuan International Monetary Fund (IMF). Komisi Hukum Nasional yang baru
dibentuk dan beranggotakan para advokat terkemuka dan andal mulai mengangkat
isu-isu pokok reformasi.
Dalam tempo sekitar satu tahun, ketika Presiden
Habibie (wakil presiden terakhir rezim Soeharto) digantikan oleh Abdurrahman
Wahid – seorang reformis yang kemudian dipaksa meletakkan jabatan dan diganti
oleh Megawati Soekarnoputri – optimisme mulai surut. Optimisme ini semakin surut
sewaktu buku ini ditulis pada akhir tahun 2003. Bukan berarti tidak ada hal
berguna yang terjadi, namun tekanan yang menurun dan perubahan yang lambat
membuat banyak orang tidak yakin bahwa sebuah transformasi bisa diwujudkan.
Peradilan korup dan tidak kompeten mulai luluh untuk melakukan reformasi, meski
sangat pelan, dan ini berawal dari puncaknya: Mahkamah Agung, yang menjadi subjek
kajian ini. Kejaksaan setidak-tidaknya merasakan adanya suatu tekanan. Sementara
itu profesi hukum juga mulai berbenah diri; dalam waktu yang lebih cepat
daripada lembaga penegaj hukum lainnya, namun juga tidak bisa dibilang
mengesankan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
menghasilkan keputusan formal dan perubahan-perubahan konstitusional. Memang,
selalu lebih mudah mengundangkan daripada melaksanakan, namun tetap saja produk-produk
mereka jarang memuaskan para pengamat, bahkan yang paling optimistis sekalipun.
Undang-undang Dasar 1945 yang hanya diniatkan sebagai undang-undang dasar kilat
itu diamandemen secara substansial dan peraturan perundang-undangan baru
diperdebatkan, dirundingkan, serta disahkan; akan tetapi semua itu diikuti oleh
janji-janji untuk melakukan perubahan lagi, karena begitu banyak kritik yang
dilontarkan.
Tulang punggung dan masa depan reformasi hukum
umumnya terdiri atas Ornop, yang sebagian besar dibentuk tak lama sesudah
pengunduran diri Soeharto terlihat membuka pintu bagi perubahan. Sarat dengan
para advokat muda yang cakap dan penuh dedikasi, bersama beberapa non-advokat,
mereka menghasilkan banyak penelitian, kritik, argumen, ide, informasi, dan
tekanan. Mereka, antara lain, adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
(PSHK), Indonesian Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (KontraS), Judicial Watch, dan juga Indonesian Center for
Environmental Law (ICEL), dan masih banyak lagi. Bersama beberapa Ornop yang
lebih dulu lahir, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan pada tahun
1970, organisasi-organisasi bantuan hukum baru berorientasi pada konstituen
khusus. Organisasi-organisasi ini tidak hanya memberikan basis bagi reformasi
hukum di masa mendatang, melainkan juga suatu kalangan profesional elite
politik baru. Meskipun banyak profesional muda masih enggan terlibat secara
politis, koalisi Ornop reformis—untuk sebuah konstitusi baru, misalnya, dan juga
proyek-proyek lain—mulai bermunculan, sehingga dapat berkembang menjadi suatu
kesatuan politis.
Signifikansi evolusi garda depan reformasi ini,
sayangnya, tenggelam dan kadang-kadang lenyap sama sekali dalam kabut pesimisme
yang kian menebal. Pesimisme ini diakibatkan oleh luar biasa kompleks dan
sulitnya mencapai perubahan substansial. Sebagian pihak merasa problemnya
sedemikian ruwet, setidak-tidaknya sebagian, karena tidak semua paham betapa
sistem hukum ternyata begitu bobrok. Sebagian besar sejarah awal kemerdekaan Indonesia
lenyap dari ingatan atau sengaja diselewengkan selama periode Orba, ketika
hanya kehebatan pemerintahan Soeharto yang diajarkan dan dirayakan. Alhasil,
relatif sedikit warga negara yang mengerti bahwa selama periode parlementer (1950-1959),
Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan advokat bekerja dengan sangat bagus,
walaupun dalam kondisi pascarevolusi yang serba apa adanya, dengan kelangkaan
sumber daya, minimnya personel terlatih, dan banyak sekali hambatan lainnya.
Sistem parlementer berakhir beberapa tahun setelah
tahun 1957, setelah tentara terang-terangan ikut berebut pengaruh politik,
sementara partai-partai politik makin turun ke politik jalanan selama periode Demokrasi
Terpimpin. Kekompakan elite politik sipil lenyap, otoritas dan kekuasaan
terkonsentrasi di Jakarta, dan kepentingan-kepentingan sempit lebih mengutamakan
keutuhan parlemen daripada proses hukum di bawah Undang-Undang Dasar Sementara
1950 yang liberal, yang dibatalkan pada tahun 1959 dengan Dekrit Presiden yang
memulihkan UUD 1945. Dalam kondisi demikian, integritas sistem hukum berantakan
dengan cepat. Ketika para jaksa dan polisi memanfaatkan keunggulan politis
mereka, para hakim akhirnya menyusul, maka korupsi pun mulai merasuki proses
hukum. Setelah kudeta pada akhir tahun 1965, tentara sepenuhnya mengontrol
negara. Ada janji untuk kembali pada hukum, tetapi tidak ada desakan yang
memadai untuk memaksa pelaksanaannya. Akibatnya, selama tiga dekade Orba, yang
terjadi hanyalah penghancuran negara Indonesia. Pernyataan ini barangkali terdengar
dramatis. Tetapi sebenarnya memang penghancuranlah yang terjadi jika kita mendefinisikan
negara modern dalam kaitannya dengan lembaga administratif dan hukum, berikut
orientasi keduanya pada kebutuhan dan cita-cita masyarakat. Di Indonesia,
lembaga-lembaga tersebut, dari puncak ke dasar, tidak hanya melakukan praktik
penyelewengan; korupsi pun makin tidak lagi dipandang sebagai korupsi,
melainkan “keuntungan sampingan”, bahkan hak, jabatan. Fungsi-fungsi mereka
pada dasarnya dikebiri ketika pemerintah makin menyerupai semacam benteng
dikelilingi wilayah yang bisa dieksploitasi.
Untuk memahami mengapa dan bagaimana negara hukum
pascakemerdekaan runtuh, mula-mula kita harus mengerti bahwa norma-norma hukum
berdiri pada sebuah basis politik. Tidak ada lembaga dan tanggung jawab negara
yang lebih jelas menunjukkan (dan lebih sering diluputkan atau disalahpahami)
poin ini daripada sistem peradilan—khususnya Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian
dan Advokat. Selain Kepolisian, walaupun dilakukan dalam cara masing-masing,
semuanya lebih bertumpu pada otoritas ketimbang kekuasaan. Otoritas tersebut
bisa dikatakan berasal dari konsesi sukarela oleh mereka yang mempunyai
kekuasaan politis, di mana dari konsesi itu memperoleh bagian otoritas sah dan
jaminan keamanan personal. Lebih dari yang lainnya, lembaga-lembaga peradilan
cenderung menjelaskan bagi warga negara, secara praktis dan simbolis, tentang
kualitas negara mereka serta sistem politik dan kepemimpinannya. Namun,
bagaimana mereka bekerja dan berinteraksi dan menjalankan kontrol efektif,
bagaimana mereka mempertahankan integritas atau tidak, bagaimana mereka
sesungguhnya membuat sebuah sistem dan untuk keperluan apa, jarang terlihat
jelas bagi warga negara. Ketika lembaga-lembaga peradilan bekerja dengan baik,
mereka mungkin menikmati semacam aura enigmatik. Ketika lembaga-lembaga
tersebut gagal, seperti yang terjadi di Indonesia, otoritas lenyap (memberi
peluang bagi diberlakukannya kekuasaan telanjang), dan itu menimbulkan
kemuakan, kemarahan, cemooh, pelemparan sepatu dan telur, dan hal lebih buruk
lainnya. Dari situ muncul pertanyaan serius mengapa lembaga-lembaga tersebut
gagal dan bagaimana membuat sistem itu seharusnya bekerja.
Kajian Sebastiaan Pompe tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebetulnya lebih dari
sekadar menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sebab, pada saat menyajikan salah
satu analisis paling cermat dan terperinci mengenai peradilan, studi ini juga
menampilkan sejarah patologi yudisial dan legal di sebuah negara yang sangat
rumit. Studi ini menempuh jalan panjang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
paling mendasar tentang kegagalan sebuah sistem peradilan—bukan cuma Mahkamah
Agung—dan segala konsekuensinya. Karya ini sangat boleh jadi akan menjadi
bacaan klasik atau, paling tidak, bacaan esensial bagi siapa saja yang berminat
dengan sejarah Indonesia modern, kompleksitas distorsi dan kegagalan
kelembagaan, dan studi komparatif badan-badan peradilan. Sekaligus kajian sejarah
yang luar biasa mendalam tentang Mahkamah Agung dan upaya amat besar untuk
mencari sebab-sebab kemerosotannya yang tak pelak melibatkan seluruh sistem
peradilan sipil tanpa banyak perlawanan. Bukan itu saja, dalam analisis Pompe
kita bisa mulai memahami mengapa reformasi hukum berjalan sedemikian alot sejak
tahun 1998, bahkan kita bisa mengamati beberapa implikasi bagi strategi-strategi
rasional reformasi itu. Tak lama setelah disertasi orisinal penulis disampaikan
di Fakultas Hukum Universitas Leiden dan
beberapa salinan sampai ke Indonesia, temuan-temuan tentang kesalahan
Mahkamah Agung menggegerkan berbagai kelompok kepentingan di Jakarta. Setelah
direvisi untuk keperluan penerbitan, studi ini tampaknya memancing perdebatan
lebih mendalam tentang isu-isu sejarah hukum dan politik Indonesia dan beberapa
diskusi penting tentang bagaimana, dan apa konsekuensinya, negara Indonesia berubah
selama lima puluh tahun terakhir.
Sulit membayangkan orang dengan kualifikasi
perbandingan hukum meyakinkan mengerjakan penelitian ini selain Sebastiaan
Pompe. Memperoleh pendidikan hukum dari Universitas Leiden, dia menekuni kajian
Indonesia dan Melayu di School of Oriental and African Studies di London, dan
meraih gelar MA (Master of Arts) di bidang hukum di Cambridge. Berbekal cukup
bahasa-bahasa berguna, termasuk bahasa Indonesia, dia juga sangat mahir dalam
variasi-variasi civil law Kontinental dan derivasi common law
turunan Inggris serta seluk-beluk evolusinya ketika semuanya itu menyebar ke
seluruh dunia melalui pemberlakuan kolonial, peniruan, dan adaptasi. Karya
terdahulu Pompe yang diterbitkan meliputi daftar panjang artikel-artikel penting
tentang beragam isu dalam hukum Indonesia dan survei paling lengkap yang ada
terhadap tulisan-tulisan tentang hukum Indonesia. Selama beberapa tahun, hingga
akhir tahun 2004, Dr. Pompe terlibat dalam sebuah program reformasi kehakiman
di Jakarta.
*Pengantar dengan judul asli "Studi tentang Runtuhnya sebuah Institusi" dalam Sebastiaan Pompe, The Indonesian Supreme Court, A Study
of Institutional Collapse, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul
Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung oleh Noor Cholis; penyunting Arsil, Dian
Rosita, Nur Syarifah; pembaca akhir Prof. Soetanyo Wignjosoebroto dan Bivitri
Susanti, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta,
2012, hlm. 9 – 13.
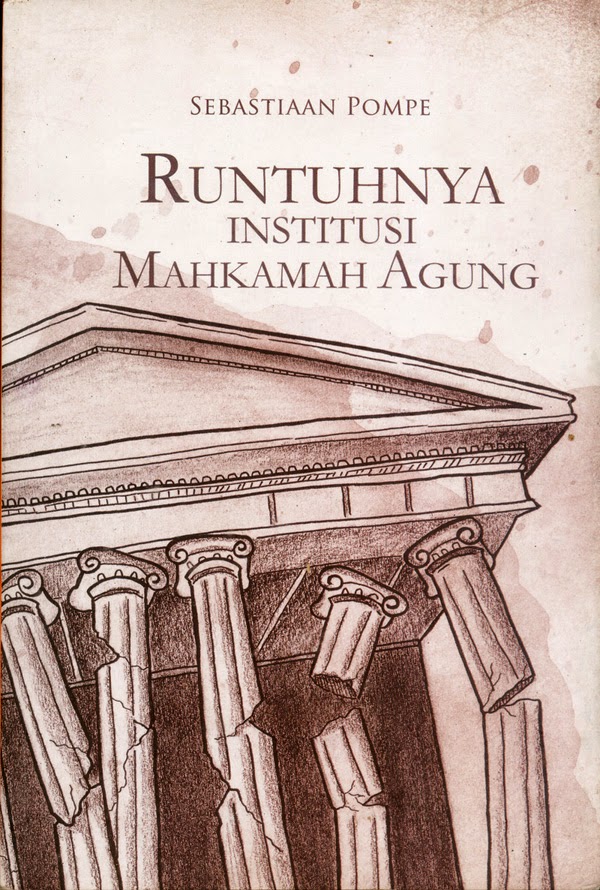



Comments
Post a Comment