Mahkamah Agung dalam Dokrtin Pemisahan Kekuasaan
 |
| Gedung Mahkamah Agung Hindia Belanda di Waterlooplein (Lapangan Banteng). Sumber foto: wikimedia.org |
Asal-usul Mahkamah Agung pada masa kolonial berakar
dalam ide-ide revolusioner Perancis mengenai struktur pemerintahan, yang
menjadi berpengaruh di Belanda, bahkan di seluruh Eropa daratan pada akhir abad
kedelapan belas. Ide-ide ini lalu ditransfer ke negeri-negeri jajahan. Doktrin
Perancis membayangkan sebuah organisasi negara yang sangat rasional berdasarkan
“bentuk ekstrem pembagian kerja, di mana masing-masing unit mengerjakan dan
hanya bisa mengerjakan satu hal.” Pemerintah, Parlemen, dan Pengadilan adalah
penguasa absolut di wilayah masing-masing, sehingga membentuk apa yang disebut pemisahan struktur kekuasaan. Tidak
ada interdependensi di antara berbagai kekuasaan Pemerintah, sehingga mereka
saling mengawasi, seperti dalam sistem perimbangan
kekuasaan yang berlaku di Amerika Serikat.
Doktrin pemisahan kekuasaan memiliki sejumlah
konsekuensi konseptual penting bagi organisasi dan kekuasaan pengadilan. Dalam
lingkup organisasional, sistem ini membedakan antara fungsi kehakiman dan
administratif dalam organisasi pengadilan. Yang disebut pertama terkait dengan
fungsi pengadilan sebagaimana mestinya, yaitu menyelesaikan sengketa. Sedangkan
yang kedua menyangkut semua hal, seperti personalia, keuangan dan manajemen
kantor (fungsi-fungsi administratif), “la
logique du système”, begitu kata orang Perancis, yang menghendaki
fungsi-fungsi administratif ini ditangani oleh Pemerintah, dan tidak oleh Pengadilan.1
Akibatnya, Perancis dan negara-negara yang hingga batas tertentu mengadopsi
sistem Perancis, seperti Belanda dan Indonesia, dicirikan oleh pembagian fungsi
bahkan dalam lembaga yudikatif. Umumnya, lembaga yudikatif menjalankan
kewenangan dan kontrol tertinggi atas fungsi-fungsi yudisial, sedangkan
fungsi-fungsi administratif, seperti administrasi pengadilan dan urusan
personalia, ditangani oleh sebuah departemen pemerintah, biasanya Departemen
Kehakiman. Departemen ini berfungsi sebagai semacam pendukung administratif
bagi lembaga yudikatif, melaksanakan permintaan (bukan perintah) dari siapa pun
yang berwenang, yang biasanya adalah Mahkamah Agung.
Aspek penting lain yang berdasarkan logika
sistematis ini terkait dengan akuntabilitas politik, terutama ihwal pendanaan.
Dari perspektif Perancis (dan Belanda), akuntabilitas dana publik adalah
kewajiban dasar konstitusional. Pekerjaan dalam mendapatkan dana (yaitu
mengajukan usulan kebijakan dan memastikan pendanaannya), dan alokasi serta
pembelanjaannya, dipandang sebagai tugas-tugas politik yang utama. Mereka yang
menerima tugas tersebut wajib menyampaikan akuntabilitas penuh terhadap
konsituensi demokratis. Sehingga orang-orang yang ditunjuk secara politis
diberi kewenangan ini dipandang bertanggung jawab oleh lembaga legislatif untuk
tindakan-tindakan mereka dalam masalah ini, kalau perlu dengan pemecatan.
Karena independensi pengadilan sulit dipertemukan dengan akuntabilitas publik, terutama
dengan adanya ancaman sanksi berupa pemecatan, akuntabilitas finansial
menghendaki pemisahan fungsi.
Sehubungan dengan kekuasaan kehakiman, doktrin
pemisahan kekuasaan tidak mengizinkan penyerobotan masing-masing kekuasaan
pemerintah. Ini berarti salah satu kekuasaan memaksa pemerintah tidak boleh
menjalankan fungsi-fungsi utama yang merupakan kewenangan dari cabang kekuasaan
yang lainnya. Maka, secara tradisional badan yudikatif tidak akan mempunyai
kewenangan untuk mengontrol kekuasaan-kekuasaan yang lain. Dalam hal pengujian peraturan
oleh Pengadilan, hal ini menimbulkan dua pembatasan jika dibandingkan dengan
sistem perimbangan kekuasaan di Amerika Serikat. Pertama, pengadilan mempunyai
hak sangat terbatas untuk menguji dan secara sangat spesifik tidak boleh
membatalkan undang-undang, atau yang disebut “undang-undang formal” dalam
sistem kontinental. Undang-undang dikualifikasikan sebagai pernyataan tertinggi
kehendak demokratis dan oleh sebab itu merupakan sumber legitimasi tunggal yang
memungkinkan dinyatakannya kekuasaan politis. Konsekuensinya, Pengadilan tidak
bisa mempertanyakan undang-undang, walaupun diperbolehkan menguji
peraturan-peraturan lebih rendah, yaitu apabila bertentangan dengan
undang-undang yang lebih tinggi. Kedua, sekalipun pertentangan dalam
undang-undang yang lebih rendah itu dijumpai, Pengadilan tidak boleh
membatalkan undang-undang terkait, tetapi hanya mengumumkan bahwa itu tidak
bisa dipakai dalam berperkara di pengadilan. Terserah badan legislatif yang bersangkutan
untuk meninjau instrumen legislatifnya sendiri.2 Ini, sudah barang
tentu, bertolak belakang dengan sistem Amerika Serikat, yang membolehkan perubahan
keputusan-keputusan Kongres karena melanggar Konstitusi.
Doktrin pemisahan kekuasaan tidak dipertanyakan
serius selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kemudian diadopsi serta
diintegrasikan ke dalam negara Indonesia modern. Tidak pernah ada perdebatan
mendasar tentang kedudukan ‘Pengadilan Tertinggi Negara’, yang kemudian dinamakan
‘Mahkamah Agung’. Penting untuk dicatat, bahwa pada akhirnya posisi Mahkamah
Agung tidak ditentukan sebagai konsekuensi, melainkan oleh pilihan berdasarkan
musyawarah.
Selama perdebatan dalam persiapan UUD 1945, para
peserta mempertanyakan apakah doktrin tersebut hendak dipertahankan. Seorang
anggota terkemuka Panitia Persiapan Undang-Undang Dasar, Mohammad Yamin,
menanyakan apakah Indonesia mesti menggunakan praktik uji konstitusional, yang
akan membolehkan Mahkamah Agung menguji konstitusionalitas undang-undang. Butir
ini menyentuh inti doktrin pemisahan kekuasaan yang jika diterima akan sepenuhnya berarti
memilih sistem perimbangan kekuasaan.
Sedemikian menguratnya tradisi hukum Perancis-Belanda
hingga panitia persiapan menolak usul Yamin. Ketua Panitia Penyusunan Undang-Undang
Dasar, Supomo, pada mulanya menyatakan secara kurang meyakinkan bahwa Indonesia
tidak cukup berpengalaman dengan peninjauan konstitusional, dan dia tidak tertutup
kemungkinan bahwa tinjauan seperti itu akan dilakukan suatu saat nanti (“...
untuk negara muda kita, terlalu dini untuk membahas persoalan ini...”). Meskipun
demikian Supomo mempunyai keberatan konseptual yang lebih mengakar. Dia
berpendapat bahwa kekuasaan penuh untuk uji konstitusional menghendaki sebuah
struktur negara yang tidak selaras dengan fondasi ideologis negara Indonesia
yang dibayangkan dalam rancangan konstitusi.3 Dalam rancangan ini, Presiden,
sangat mirip dengan seorang bapak patrimonial tradisional yang dipandang
sebagai kepala keluarga, dengan tanggung jawab memimpin dan menyatukan rakyat.
Presiden mewujudkan kesatuan masyarakat dan dalam kapasitas itu dia berada di
atas semua golongan. Jelas, sebuah Mahkamah Agung yang kuat, sebagaimana
diusulkan Yamin, dengan kewenangan menguji konstitusionalitas
perundang-undangan, bertentangan dengan gagasan ini.4 Supomo
menegaskan:
... dalam hemat saya, Ketua Yang
Terhormat, konstitusi ini tidak didasarkan pada pemisahan pokok tiga kekuasaan Pemerintah,
sehingga lembaga yudikatif tidak perlu diberi kekuasaan membuat undang-undang.
Dalam konteks Indonesia kontemporer, usulan Yamin
dan penolakan terhadapnya banyak diakui sebagai sebuah peristiwa penting dalam
hukum tata negara Indonesia.5 Usulan itu dipandang sebagai sebuah
prakarsa serius yang akan diterima sekiranya bukan karena Supomo yang tidak
imajinatif dan reaksioner.6 Inti gagasannya adalah Indonesia sangat
mungkin tampil sebagai negara yang berbeda kalau saja usulan itu diterima.
Argumen ini tentu saja bersifat spekulatif, tetapi jelas sangat memikat.
Kegagalan Mahkamah Agung dan Pengadilan mempertahankan otonomi mereka dari
campur tangan pemerintah setelah kemerdekaan membuat orang berpikir-pikir boleh
jadi mereka akan jauh lebih baik sekiranya menganut sistem konstitusional
berbeda. Bagaimanapun juga, realitas sejarah memperlihatkan bahwa pada masa
kemerdekaan, Indonesia menganut doktrin pemisahan kekuasaan Perancis-Belanda.
Terutama di bawah Orde Baru, perjuangan untuk mengubah Mahakamah Agung dan
peradilan kian terfokus pada doktrin ini dan beberapa ciri menonjolnya. Jika
perubahan itu tiba, maka doktrin pemisahan kekuasaan adalah pertama kali yang
akan diadopsi.
________________________________________
Catatan Akhir
1. Untuk menjamin independensi kehakiman, rutinitas
kerja menghendaki agar departemen pada dasarnya bertindak sebagai saluran
administratif bagi permintaan-permintaan pengadilan. Kendati demikian, doktrin
ini tidak membolehkan lembaga yudikatif menginstruksikan departemen untuk
mewujudkan fungsi-fungsi administratif, tetapi hanya bisa memintanya.
2. Tentu ini adalah deskripsi amat sederhana sistem
tersebut, yang bagaimanapun juga tidak menjelaskan perkembangan-perkembangan
sesudah Perang Dunia Kedua. Jika Perancis melembagakan Cour Constitutionnel,
di Belanda pengadilan boleh menguji keputusan-keputusan Parlemen sehubungan
dengan perjanjian internasional, meskipun tidak jika berkaitan dengan
Undang-undang Dasar. Perkembangan-perkembangan ini bukan tidak ada
sangkut-pautnya sama sekali dengan konteks Indonesia, karena Pemerintah
Indonesia mempertahankan diri dengan gigih terhadap tuntutan-tuntutan judicial
review, misalnya, dengan rujukan-rujukan ideologis pada sistem usang
Perancis sebelum perang.
3. Yamin, Naskah persiapan, h. 341. Ada
persoalan dalam kalimat penting yang disampaikan Yamin. Setelah pemikiran yang
merujuk model-model konstitusional Barat, kalimat itu berbunyi: “Akan tetapi
di negeri democratie perbedaan atau perpisahan antara tiga djenis kekuasaan itu
tidak ada.” Pernyataan ini diikuti oleh penjelasan tentang sistem rancangan
undang-undang Supomo. Kalimat Yamin itu tidak masuk akal, karena pemisahan
kekuasaan Pemerintah tidak dikenal di negara-negara demokrasi. Karena kalimat
itu dimulai dengan sebuah negasi yang menunjukkan kontras dengan perkataan
sebelumnya, mestinya lebih baik jika dibaca dengan perkataan sesudahnya, yang
membicarakan ide-ide demokrasi yang mendasari konstitusi Supomo. Jika
penafsiran ini tepat, dan saya menganggapnya begitu, ada sebuah kata yang
hilang dalam catatan Yamin, yang aslinya mestinya berbunyi kurang lebih begini:
“Akan tetapi di negeri ini, democratie perbedaan atau perpisahan antara tiga
djenis kekuasaan itu tidak ada.”
4. Yamin, Naskah persiapan, h. 232-36. Menarik
untuk diperhatikan, dalam sebuah artikel tentang Negara Federal yang terbit dua
tahun kemudian, Supomo mengungkapkan ide-ide yang sangat sejalan dengan
pemikiran-pemikiran yang diusulkan Yamin. Lihat Mimbar Indonesia 7
Februari 1948. Supomo mengatakan: “Saya yakin bahwa mungkin perlu juga bagi
Indonesia untuk memiliki sebuah ketentuan konstitusional yang memberi
kewenangan Pengadilan, seperti Mahkamah Agung Federal, untuk meninjau konstitusionalitas
semua perundang-undangan, dari pihak-pihak berwenang federal maupun
negara-negara bagian.” Lihat juga A.A. Schiller, The Formation of Federal
Indonesia 1945-1949 (Den Haag/Bandung: Van Hoeve tahun 1955), h. 294. Perlu
diingat bahwa pandangan ini tidak bertentangan dengan pendapat-pendapat
sebelumnya yang dikemukakan Supomo. Tidak seperti negara-negara kesatuan,
struktur federal menghendaki tinjauan legislatif oleh Pengadilan sebagai
instrumen untuk mengkoordinasikan rezim-rezim regulasi negara-negara bagian.
5. A. B. Nasution, The Aspiration for
Constitutional Government in Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1992), h. 122; T. Mulya Lubis, In Search of Human Right (Jakarta:
Gramedia, 1993), h. 119, J. C. T. Simorangkir, Hukum dan Konstitusi
Indonesia, Jilid 2 (Jakarta: Gunung Agung, 1986), h. 37; Sri Soemantri, Hak
Menguji Material di Indonesia (Bandung: Alumni, 1986), h. 47-48. Walaupun
pentingnya usulan Yamin sangat jelas dalam pengertian politik-konstitusional,
mungkin terlalu berlebihan upaya menyandangkan signifikansi historis
kontemporernya. Ada indikasi bahwa para pendukungnya tidak menyadari bahwa isu
itu sangat penting secara fundamental, dan bahwa judicial review adalah
salah satu dari banyak balon panas yang melayang-layang dalam perdebatan itu.
Supomo tidak memikirkan usulan itu cukup serius untuk membahasnya secara
tuntas; jawabannya ambigu dan serampangan. Para anggota panitia persiapan
lainnya tampaknya juga tidak menganggap itu sebagai isu penting, yang sangat
kontras dengan sikap mereka terhadap masalah-masalah lain, seperti hak asasi
manusia. Orang bisa melukiskan Yamin sebagai seorang visioner di padang pasir,
tetapi waktu itu Yamin tidak mendesakkan isu tersebut sama sekali. Malah,
bukannya tampil sebagai pemikir politik cerdas berwawasan jauh ke depan, Yamin
justru merupakan bagian dari persoalan itu sendiri. Punya pikiran tajam, Yamin
juga punya reputasi kelewat bersemangat dan bertele-tele, dan agak congkak. Dia
membuat letih beberapa anggota panitia dengan pidato-pidato tak putus-putus dan
banyak interupsi. Ini merusak integritasnya, justru karena tak terhitung
komentar dan saran yang bertebaran ke segala arah dan kadang-kadang tidak punya
koherensi internal serta fokus. Sikapnya terhadap judicial review adalah
contoh relevan. Akhirnya, walaupun autentisitas bagian perdebatan ini tidak
diragukan, perlu diingat bahwa kita hanya mempunyai keterangan dari Yamin
tentang apa yang terjadi, dan belakangan dinyatakan bahwa catatan itu mungkin
tidak benar-benar bisa diandalkan, boleh jadi sudah disunting untuk
membesar-besarkan peran Yamin di dalamnya. Lihat M. Simandjuntak, Pandangan
negara integralistik (Jakarta: Grafiti, 1994), h. 17-21, 67-68, 255-57, dan
Suara Pembaruan, 19 Juni 1993, dikutip di dalamnya.
6. Sebagai ahli hukum kawakan, anggota elite Jawa
tradisional, dan bagian tak terpisahkan dari elite birokrat yang mengalami
eropanisasi di tanah jajahan, Supomo tidak pernah menjadi pendukung perubahan
radikal. Kecondongan personal dan profesionalnya mendukung pembaruan
bertingkat-tingkat, tertib dan rasional, bukan pembaruan radikal dan
impresionistik. Usulan Yamin luar biasa karena dalam beberapa segi dia termasuk
dalam kelompok Supomo. Tetapi dia pembangkang. Kariernya di kemudian hari
sebagai pelaku kudeta gagal, penyair, dan politikus patriarkal dalam sebuah era
di mana Pengadilan sangat terpinggirkan mengungkapkan bahwa karakter Yamin jauh
lebih kompleks daripada Supomo yang berbakat tetapi agak membosankan.
Dipetik dari Sebastiaan Pompe, The Indonesian Supreme Court,
A Study of Institutional Collapse, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
dengan judul Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung oleh Noor Cholis; penyunting
Arsil, Dian Rosita, Nur Syarifah; pembaca akhir Prof. Soetanyo Wignjosoebroto
dan Bivitri Susanti, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan,
Jakarta, 2012, h. 31-36

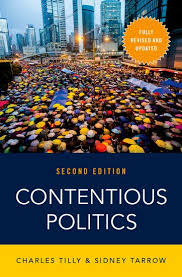

Comments
Post a Comment